“Lex, lo nonton QFF nggak?” Pertanyaan itu muncul dari beberapa sahabat saya. Mulai dari sahabat gay, lesbian, hingga sahabat hetero. Tahun ini adalah tahun keenam diadakannya QFF alias Queer Film Festival di Jakarta, di mana di ajang ini diputar film-film pilihan bertema LGBT. Sejak dua tahun lalu, festival ini juga merambah ke luar Jakarta, yaitu Bali dan Yogyakarta. Saya, selalu ikut festival ini sejak tahun pertama. Kata “ikut” di sini berarti nonton. Mulai dari festival ini memutar film yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari tangan hingga makin akbar dan jadi liputan media seperti sekarang.
Semakin banyak film yang diputar, anehnya makin sedikit film yang saya tonton jika saya membuat perbandingan jumlah film yang diputar vs film yang ditonton. Kenapa ya bisa begitu? Mungkin karena acara ini sudah jadi rutinitas tiap tahun sehingga kurang spesial lagi? Mungkin karena film-film yang diputar makin mudah dicari DVD-nya? Mungkin karena saya mulai taken for granted terhadap acara ini? Hhh, entahlah.
Jangan salah, saya tetap bersemangat untuk hadir. Berdandan rapi, berjanji temu dengan beberapa sahabat untuk ketemu di Opening QFF yang diadakan di Blitz Megaplex, Jumat 25 Agustus 2007. Opening begitu meriah, Blitz di-queer-kan oleh QFF. Ramai suasana dengan sejumlah selebriti, dan sebagian besar yang hadir di sana adalah gay/lesbian/transgender, ditambah sejumlah sahabat hetero yang GLBT-friendly. Makin meriah dengan hiburan musik yang menggelegar.
Apakah saya merasa at home? Entahlah, ada perasaan-perasaan tidak berada di "rumah" pada tahun ini. Saya merasa tersesat dan ingin pulang, sebagaimana perasaan yang saya rasakan ketika hadir ke perta pernikahan saudara sepupu yang tidak terlalu saya kenal dengan baik. Ah, saya putuskan setelah tugas saya selesai, yaitu setelah bertemu teman-teman yang sudah janjian ketemu di sana, saya akan langsung cabut.
Tiktoktiktok. Acara utama pemutaran film pun sebentar lagi akan dimulai. Saya sudah memutuskan tidak akan nonton, karena sahabat gay saya bilang, “Nggak usah nonton film ini deh, lo bisa ketiduran. Boring abis.” Okelah, bagus, saya akan pulang. Selagi berpamitan dengan sahabat-sahabat di sana, bahu saya ditepuk oleh lelaki gay sahabat saya sesama mantan volunteer di QFF dulu.
“Sombong ya, nggak balas e-mailku,” katanya. Sahabat saya, sebut saja namanya Handi melanjutkan, “Mau nonton?”
“Nggak, aku mau pulang bentar lagi. Kamu? Kok belum masuk?”
“Aku udah nonton film ini. Tapi nanti jam 10 mau nonton Rush Hour sama yayangku dan adiknya.”
Handi mengeluarkan katalog QFF, “Nonton film apa aja tahun ini?”
Sambil ikutan browsing daftar film dalam katalog, saya menjawab, “Nggak banyak sih. Lebih ikut acara off-air-nya.”
“Ikutan juga tahun ini?” tanyanya lagi.
“Iya, dua,” kata saya, sambil menunjuk acara yang dimaksud.
Handi dengan bersemangat berceloteh tentang film-film yang ingin ditontonnya, sehingga saya pun tertular semangatnya hingga lupa akan keinginan saya untuk pulang
Mendadak Handi mendongak, memandang ke sekeliling ruangan. “Aku senang sekali lho acara ini. Coba kamu lihat. Gay, lesbian, trans, straight, semuanya beredar di ruangan ini.”
Saya memandang ke ruangan yang luas tersebut. Suasananya tidak seramai satu jam sebelumnya, namun kita masih bisa melihat tamu-tamu Q dan tamu-tamu Blitz yang datang untuk nonton.
“Kita nggak perlulah demo teriak-teriak di jalanan minta pengakuan. Cara ini lebih efektif. Kamu liat, gimana kita tuh secara nggak langsung mendapat pengakuan. Kita ada. Di sini. Di tempat publik. Punya acara sendiri.” Saya terdiam, perlahan mencerna kata-kata Handi.
“Lihat katalog ini, lihat makin banyak sponsornya. Lihat bagaimana perusahaan-perusahaan komersil memasang iklan di sini. Mereka melihat kita sebagai aset penting yang perlu “digandeng”.
Saya mengambil napas dalam-dalam memandang Handi yang masih penuh semangat bercerita. Perlahan-lahan saya sadar saya tahu apa yang membuat saya lupa dan tersesat di tempat ini. Seperti kisah Peter Pan yang bisa terbang hanya dengan berpikir bahagia, saya mungkin terlalu lama tinggal di Neverland atau mungkin tak sadar bahwa saya sudah kembali ke alam realitas dan umur saya pun bertambah tidak seperti Peter Pan yang tetap jadi anak-anak. Saya tidak bisa terbang lagi, namun Handi meniupkan debu peri pada saya sehingga saya pun kembali terbang dan ingat alasan saya berada di Neverland.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Club Camilan
14 years ago

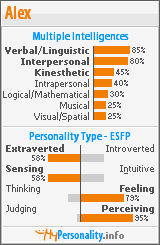
1 comments:
andai debu peri itu melekat pada semua manusia hingga kita bisa terbang bersama...
Post a Comment