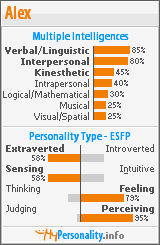Sejak dulu saya terobsesi dengan makhluk abadi yang bernama vampir. Entah kenapa. Mungkin karena pada dasarnya manusia memiliki pertanyaan-pertanyaan tak terjawab tentang kehidupan, kematian, dan keabadian.
Konsep makhluk jejadian yang bersosok manusia mati namun “bernyawa” di muka bumi dengan berbagai kutukan yang dibawanya membuat otak saya yang kerdil ini memikirkan banyak hal tentang apa, bagaimana, kenapa mereka hidup.
Saya memikirkan kehidupan imortal para vampir ini dalam konsep religiusitas, bagaimana mereka terkoneksi dengan penciptanya dan menjadi pencipta dalam kekuatan darah yang mengalirkan kehidupan.
Ada gagasan romantis, psikoseksual, dan religiusitas yang dekat dengan kehidupan homoseksual dalam kehidupan imortal vampir ini.
Kisah vampir nyaris tak lepas dari kisah cinta. Tentang cinta abadi yang tak kenal waktu. Tentang cinta yang menerabas kematian. Tapi saya tidak mau bicara soal gagasan romantisme di sini. Seisi dunia sedang tergila-gila pada Edward, bahkan saya juga, dan cukuplah dulu saya menuliskannya sekali.
Kisah vampir juga tidak lepas dari kutukan keabadian. Yang membawa saya dalam pertanyaan tentang kenapa vampir diciptakan. Siapa penciptanya. Apakah ada Tuhan di sini? Walaupun tujuan itu kembali lagi ke niatan si pengarang, tapi dilihat dari sudut mana pun vampir adalah produk agama Kristen. Atau lebih tepatnya pengingkaran terhadap ke-Kristen-an. Bisa dilihat bagaimana vampir hasil generasi awal digambarkan takut terhadap salib dan air suci.
Bram Stoker menulis novel Dracula pada tahun 1897, menggunakan kemarahan Count Dracula terhadap Tuhan karena tega merenggut istri yang dicintainya padahal dia sedang membela Tuhannya dalam Perang Salib. Dia marah karena para pemuka agama menyatakan istrinya tidak bisa masuk surga karena meninggal akibat bunuh diri. Jadilah sang count mengingkari Tuhannya dan menjadi makhluk terkutuk yang hidup dari darah.
Bercerita tentang vampir tidak bisa lepas dari nama Anne Rice. Sejak tahun 1976 dia menulis Vampire Chronicles-nya dalam konsep atheis. Sosok-sosok vampir yang diciptakan Anne Rice dalam karya-karya fiksinya memuat teori bahwa ada makhluk yang tercipta jauh sebelum Kristus muncul. Ketika manusia masih memuja matahari dan bumi ini sendiri. Ada kekuatan besar, makhluk abadi yang tak tersentuh oleh kematian yang menitiskan kekuatannya melalui darah.
Wes Craven, salah satu raja film horor, menciptakan teori baru tentang vampir. Teori ini begitu jauhhh hingga sulit diterima oleh, yeah, paling tidak oleh saya. Dalam film Dracula 2000, Wes Craven menyatakan bahwa Dracula sesungguhnya adalah Yudas Iskariot, yang dikutuk untuk berjalan di muka bumi sebagai makhluk yang tidak bisa mati, dan ditolak masuk surga dan neraka. Teori ini berusaha menjelaskan kenapa Dracula takut pada benda-benda perak, karena Yudas dibayar dengan perak untuk pengkhianatannya terhadap Yesus.
Bram Stoker dan Wes Craven memberikan ketenangan pada Dracula ciptaan mereka dengan memulangkan sosok imortal pada “surga”. Memberikan mereka kematian dan akhir yang mereka dambakan. Berbeda dengan Anne Rice dengan sosok-sosok vampir ciptaannya yang tidak takut pada hal-hal bersifat agama modern, yang menurutnya adalah produk ciptaan manusia. Mereka hidup jauh sebelum manusia modern muncul dan menciptakan agama.
Begitu banyak lesbian yang lari dari agamanya ketika mengetahui bahwa mereka dicap sebagai makhluk terkutuk. Agama hanyalah pengekang, dan dengan bangga mereka menolak Tuhan mereka. Tapi banyak dari mereka yang gelisah. Seperti halnya Dracula yang mencari cinta sejatinya pada Wilhemina Harker, lesbian-lesbian itu juga mencari Wilhemina Harker mereka. Mereka menganggap diri mereka sebagai makhluk kegelapan. Yang bisa musnah terbakar matahari jika berani keluar pada siang hari. Yang akan dikejar untuk dibunuh oleh para pemburu makhluk terkutuk ini. Dan jadilah mereka makin marah dan jahat. Mereka jadi menggertak lebih dulu, menyerang dan menakuti sebelum diserang. Dan jadilah lingkaran kebencian yang tak putus.
Begitu banyak kebencian dan kemarahan yang dirasakan oleh sang vampir dan lesbian-lesbian yang jauh dari intisari mereka sendiri. Kenapa aku? Itu juga pertanyaan yang ditanyakan oleh Dracula dan Lestat dalam Vampire Chronicles.
Pada era tahun 1990-an muncul teori baru “vampir berjiwa”. Joss Whedon memperkenalkan Angel sebagai sosok vampir berjiwa dalam Buffy the Vampire Slayer. Anne Rice juga menampilkan sosok Louis sebagai vampir berjiwa dalam Vampire Chronicles-nya. Vampir-vampir yang begitu simpatik sehingga bisa membuat manusia jatuh cinta dan rela menyerahkan diri mereka padanya. Dan yang terbaru adalah Edward ciptaan Stephenie Meyer yang gigitannya berhasil menciptakan histeria massa.
Sebut mereka vampir-vampir vegetarian. Louis, Angel, Spike, Edward. Mereka adalah vampir yang memutuskan untuk mengontrol dahaga mereka dengan tidak menyantap darah manusia. Kevegetarian mereka itulah yang menjual mereka menjadi budaya pop. Pencitraan ini secara tidak langsung juga memengaruhi cara pikir masyarakat untuk bisa menerima hal absurd sebagai suatu realitas romantis.
Konsep vampir untuk target remaja kebanyakan berkutat pada romantisme. Keseksian sang vampir yang selalu bisa menaklukkan makhluk mortal bernama manusia. Tapi tidak semua manusia. Hanya manusia-manusia terpilih yang bisa dicintai oleh vampir-vampir ini. Manusia-manusia kegelapan ini menemukan kembali inti dirinya melalui cinta. Vampir seharusnya makhluk mati, tapi mengapa ada manusia yang bisa membuat jantungnya serasa berdenyut kembali?
Saya selalu menarik benang merah antara percintaan vampir dengan manusia ini dengan kisah cinta homoseksual. Cinta terlarang yang tidak bisa bersatu. Sejak awal, vampir memang tidak lepas dari seksualitas dan sensualitas. Anne Rice bahkan menciptakan pertanyaan, “Jika kau hidup selamanya, apakah kau akan menghabiskannya hanya dengan satu gender atau kau mencoba segala kemungkinan?” Bahkan ketika mengetahui putranya gay, Anne Rice menyuruh putranya membaca Vampire Chronicles-nya.
Kini seiring dengan perubahan sosok vampir dalam budaya pop, dari makhluk sadis pemangsa manusia, vampir sering kali ditampilkan sebagai sosok dengan jiwa yang bersih. Jika selama seabad lamanya vampir menjadi tokoh pemangsa manusia, makhluk pengisap darah, kini mereka dianggap “selevel” dengan manusia. Jika memantulkan sosok vampir berjiwa ini dalam cermin kaum homoseksual, belakangan ini pencitraan homoseksual pun tidak semata-mata menunjukkan kevampirannnya, eh, kehomoseksualitasnya, di masyarakat, tapi menyorotkan jiwa mereka yang berkilau. Kaum lesbian/gay pun belakangan ini tidak melulu dianggap sebagai pemangsa kaum hetero.
Jadi teorinya, jika semakin sering manusia dipaparkan pada absurditas yang kemudian dianggap “normal”, paradigma masyarakat pun akan ikut berubah. Mungkin kita harus berterima kasih pada kreator-kreator cerita vampir ini yang membuat masyarakat bisa menerima keanehan cinta antara sesama jenis, eh, kisah cinta antara vampir dan manusia sebagai kisah cinta romantis yang wajar.
Ah, saya mengoceh panjang-lebar lagi tentang isi otak saya yang kebanyakan edannya. Sudah jam setengah tiga pagi... lebih baik saya sudahi dulu tulisan ini. Kapan-kapan kita lanjut lagi untuk topik ini :).
@Alex, RahasiaBulan, 2008
Setiap kali menonton film atau serial TV saya selalu terpesona pada tokoh antagonis. Dulu saya ngefans banget sama Amanda (Heather Locklear) dalam serial Melrore Place, Brenda (Shannen Doherty) dalam serial Beverly Hills 90210, dan yang terbaru Blair (Leighton Meester) dalam serial Gossip Girls. Buat saya perempuan-perempuan seperti itu selalu menarik dan memesona. Perempuan harusnya bitchy seperti itu. Perempuan yang tidak ragu-ragu melibas lawannya jika dia tahu bahwa dia punya alasan melakukannya. Saya menyukai kejujuran mereka untuk menunjukkan kekejian dibanding bersikap manis layaknya serigala berbulu domba. Paling tidak, perempuan-perempuan ini adalah orang yang tidak munafik dan tidak pengecut.
Makin sadis perempuan-perempuan menghabisi lawannya, saya makin suka. Perempuan-perempuan itu bagai memanifestasikan sisi gelap dalam diri saya.
Dunia membutuhkan tokoh-tokoh seperti itu. Keberanian mereka bersikap antagonis membuat hidup jadi menarik. Saya dan sahabat saya di kantor saling menikam terang-terangan setiap hari. Apalagi kalau rapat, wah, kami saling menghabisi, dan peserta lain di kantor biasanya menanti dengan seru. Tapi dia sahabat terbaik saya di kantor, karena apa pun yang terjadi dia selalu bisa mengandalkan saya untuk menjadi penyeimbang sikap antagonisnya. Demikian pula sebaliknya. Ibarat film kalau tidak ada Hannibal Lecter, Joker, atau Lex Luthor kan mendingan pulang aja nggak usah nonton. Ukuran seorang pahlawan dinilai dari musuh yang dihadapinya.
Manusia selalu memiliki dua sisi. Demikian pula kalau kita memerhatikan tokoh-tokoh antagonis itu. Kebaikan dan kejahatan. Hitam dan putih. Tidak selamanya saya jadi miss nice, lebih sering saya jadi bad girl. Dan saya juga tidak suka pacaran sama cewek jaim yang sok manis. Plis deh, mendingan pulang aja ke kampung sana kalo mau jaim. Hayo tunjukkan kebengisanmu. Saya adalah orang yang egois, pemarah (you ain't see nothing yet, baby, kalau belum lihat saya ngamuk), saya bisa membuat orang sinting karena saya senang membuat hidup orang menderita kalau saya sudah membencinya.
Kalau di hadapan pasangan saja kita harus jaim, buat apa menjalin hubungan? Ketika saya kepingin jadi tokoh antagonis, pasangan juga harus menyeimbangkan saya. Saya paling benci punya pasangan yang sering sok ngasih nasihat, “plis jangan begitu, plis jangan begini.” Plis deh, jangan macam-macam sama saya. This is me. Take it or leave it.
Orang sering kali bilang, dia mencari pasangan yang bisa menerima dirinya apa adanya. Bagi saya, apa adanya ya seperti adanya. Bukan menerima keadaan yang sudah ada tapi menerima segalanya, bahkan yang terburuk dari pasangan. Menerimanya ketika dia berada dalam keadaan lemah dan buruk. Tapi di balik semua itu sang pasangan juga bisa menghasilkan yang terbaik dari hubungan karena hasil dari saling pengertian itu.
Kalau nggak suka sama sikap saya, jangan pacaran sama saya. Itu prinsip yang selalu saya junjung. Nggak usah deh ngasih-ngasih nasihat yang sok bener. Saya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jangan berusaha mengubah saya menjadi orang yang “benar” menurut versinya. Saya tahu saya jadi orang jahat saat saya ngamuk berat atau ketika emosi saya pecah tak terkendali. Tapi sehabis jadi penjahat, saya hanya ingin tahu bahwa masih bisa pulang ke pelukannya.
Saya ingin punya pasangan yang kepadanya saya bisa membuka seluruh topeng saya, memperlihatkan seluruh taring mengerikan yang saya miliki di hadapannya. Saya bisa jadi gabungan Amanda, Brenda, dan Blair, dan dia masih mau memeluk saya dan berkata, “Ssst, it's okay. Ada aku di sini mendampingimu.”
So what if I'm the bad guy? Do you still love me?
@Alex, RahasiaBulan, 2008
"Sometimes one creates a dynamic impression by saying something,
and sometimes one creates as significant an impression by remaining silent." (Dalai Lama)
Katakan padaku seperti apa suara kebenaran itu? Apakah suaranya itu bergaung lantang, membahana hingga ke pelosok desa? Ataukah suara kebenaran itu hanya bisa didengarkan melalui keheningan?
Suara kebenaran yang dilantunkan seseorang, dinyanyikan ceria oleh pendengar lain, menyebar ke seantero negeri. Diaransemen berulang-ulang sesuai mood si penyanyi, dibuat karaokenya, dipancarkan oleh anak-anak pengamen jalanan. Semua orang senang mendendangkannya setiap hari, seperti lagu-lagu dari radio yang membahana didengar kala perlu dimatikan saat membosankan.
Ada pula suara kebenaran lain yang disimpan dalam keheningan. Diperam dan meresap melalui sunya meditasi. Yang kemudian bergema dalam lantunan tanpa kata-kata, merasuk ke dalam benak mereka yang mau mendengarkan. Gema itu memantul, lalu menyebar ke dinding sukma, mengalir dalam darah.
Biarlah suara-suara sumbang, tuduhan, pengkhianatan versi XP, gosip paling pas, komentar-komentar sahih berseliweran dalam oksigen yang dihirup bersama-sama dengan riang gembira. Oksigen, untuk kebutuhan hidup. Oksigen, untuk mempertahankan diri. Oksigen, untuk yang lain-lain.
Biarlah semua orang mempercayai kebenarannya masing-masing. Apa pun yang kulakukan, pilihan apa pun yang kuambil, aku tetap salah, kau yang (tampak) benar - tanpa definisi yang jelas arti kebenaran itu.
Percuma, kan? Dan mungkin,
“Silence is sometimes the best answer" (Dalai Lama)
@Alex, RahasiaBulan, 2008
 Oleh: Alex
Oleh: Alex
Kemajuan teknologi membuat manusia merasa harus terus terkoneksi. Teknologi yang berubah demikian cepat membuat kita terkadang lelah harus berkejaran dengan kecepatan perubahan. Dan bagaimanapun, kita selalu kalah mengejar kecepatannya.
Saat kita bisa santai, kita merasa berdosa karena merasa terlalu egois, padahal kita harus stay connected demi teman-teman maya kita. Kita jadi manusia kesepian yang mencari dan terus mencari kebahagiaan di luar diri kita sendiri. Kita menarik siapa pun yang ada di dunia maya, berpikir bahwa maya itu bisa jadi realitas dan realitas adalah kenyataan yang bisa kita tunda kapan saja. Sahabat, kekasihmu, atau korban tepe-tepemu hidup di dalam laptop dan handphone.
Orang yang ada di depan mata kadang-kadang kita abaikan karena kita sering berpikiran, “Ah dia selalu ada.” Tapi yang jauh dan maya selalu kita cari-cari karena mereka tidak selalu ada dan karena ke-maya-an mereka itu, kita jadi merasa terus-menerus haus ingin “menyentuh”nya. SMS/MMS/YM/telepon yang masuk mengingatkan otak kita bahwa “Hai, aku di sini. Please stay connected with me.”
Kita jadi takut kehilangan tali koneksi yang rapuh itu. Rayuan, cinta, dan pemujaan lewat dunia maya terasa samar namun jiwa egois kita tidak mau kehilangan semua itu. Ibarat menggenggam udara. Kita terus berpegangan pada dunia semu yang rapuh karena takut kehilangan. “Masih ingat janjimu untuk mencintaiku selamanya?” Berapa lama selamanya dalam kemayaan? Seperti apa bentuk cinta yang semu? Saat dia jauh, kau berusaha menggapai-gapainya, menariknya kembali. Cukup dengan satu pesan pendek. SMS/YM/E-mail. “Masihkah ada aku dalam hatimu?”
Padahal perasaan itu perasaan yang semu. Ilusi. Yang mati-matian kita pertahankan karena kita takut kesepian. Kita mencari dan terus mencari sahabat, kekasih, atau siapa pun yang bisa kita pegang. Apalagi dalam dunia lesbian, yang konon mencari pacar sangatlah sulit. Kau berpegangan pada seseorang mati-matian. Terkadang, walaupun maya, kaupuaskan dirimu dalam kemayaan itu. Dan di antara itu ada manusia-manusia yang cuma berani di dunia maya tapi gentar menghadapi kerasnya kenyataan hidup. Ibarat burung onta memilih menyerudukkan kepalanya di pasir. Di dalam pasir dia berteriak, "Jangan tinggalkan aku ya. Aku takut tidak punya siapa-siapa."
Kita tidak perlu bertemu secara fisik, selama aku bisa curhat denganmu, menceritakan hari-hariku padamu, mengirimimu SMS, meneleponmu di saat senggang. Setelah telepon dimatikan, setelah SMS/YM berakhir lalu apa? Kamu tetap merasa haus, ibarat dahaga yang dituntaskan dengan air laut. Ada “it” yang hilang, yang tidak bisa tergantikan. Dan saat kau pulang ke dunia realitasmu di ujung waktu, kau baru sadar bahwa kau sudah mengenyahkan banyak orang untuk memegang “kesemuan” itu.
Makin lama kau merasa dirimu kosong. Hampa, walaupun kau berusaha menarik sebanyak mungkin udara ke paru-parumu. Semakin banyak kau menarik udara, kau tidak merasa penuh, tapi kau melayang. Dan itu makin membuatmu takut. Takut akan kehilangan kontrol diri dan jejakanmu di bumi. Rasanya gamang dan menakutkan.
Kita takut kehilangan rasa semu yang kita terima dari orang-orang di dunia maya. Kita ingin berpegangan dengan rasa itu tak peduli konsekuensinya. Kita menyimpan rasa itu dalam ruang kosong seperti kita menyimpan barang di gudang. Disimpan dulu, yang penting ada di gudang, dan bisa kita pakai kapan saja kita mau. Hingga lama kelamaan barang tersebut akan berdebu dan berubah fungsi menjadi sampah gudang dengan sendirinya.
Stay connected. Seharusnya teknologi membuat manusia terkoneksi, membuat manusia makin punya waktu untuk orang-orang yang disayanginya. Tetapi kenapa banyak manusia jadi makin kesepian?
@Alex, RahasiaBulan, 2008
Sejak kecil kita sudah dicekoki dengan beragam kisah dongeng putri dan pangeran yang bertemu lalu jatuh cinta kemudian hidup bahagia selamanya. Belum lagi dongeng-dongeng lain tentang cinta tiada tara dan kesempurnaan kesetiaan. Indah, bukan? Dongeng ini tidak hanya untuk perempuan hetero, banyak lesbian juga memiliki impian ala Cinderella. Belakangan ini saat menjelajahi dunia maya lesbian, saya jadi gatal kepingin mengintrepretasikan kembali dongeng ini dan menabrakkannya dalam dunia lesbian. Otak saya mulai bertanya, "Bagaimana jika?"
Bagaimana jika sang Cinderella itu sebenarnya perempuan pemalas yang miskin dan kerjanya hanya mejeng di depan pintu menunggu pangeran, eh, putri cantik lewat. Setelah putri cantik dan tajir itu lewat si Cinderella sengaja melakukan tepe-tepe dan melancarkan segala rayuannya untuk memancing sang putri agar mau memacarinya. Oh, jangan salah, setelah berhasil memacari sang putri, si Cinderella menganggapnya sebagai kesuksesan luar biasa dan tidak pernah lupa mengingatkan semua orang bahwa walaupun dia cuma perempuan miskin dan tidak ada apa-apanya, dia bisa mendapat putri hebat dan kaya raya.
Bagaimana jika Snow White sebenarnya perempuan paling menjengkelkan seistana, tiap hari dia hanya sibuk bercermin sambil mengaku-ngaku betapa cantik dan sempurna dirinya dan tanpa henti mengingatkan semua orang bahwa dirinya cantik, cantik, dan luar biasa cantik. Hingga suatu hari ibunya kesal dan memutuskan untuk mendepaknya ke hutan. Lalu di sana Snow White sengaja diracuni para kurcaci supaya dia bisa diam. Karena setelah di hutan pun dia ternyata masih narsis dan curhat tak kenal henti dengan tujuh kurcaci hingga mereka sakit telinga mendengarnya.
Bagaimana jika Sleeping Beauty hanyalah perempuan kesepian yang tinggal di menara gadingnya? Parno menghadapi dunia nyata, dia lebih suka hidup dalam ilusi indah tentang kesempurnaan cinta. Tiap hari dia bermimpi bisa didatangi oleh pangeran eh, putri impiannya. Berkhayal dalam ilusi cinta sempurna, ia terus-menerus bertanya, Kapan ya aku bisa dicintai dengan apa adanya diriku? Kapan ya keindahan hidup kudapatkan? Kapan ya aku akan seperti putri-putri lainnya?
Itulah yang tak pernah terlihat dalam ilusi dongeng yang kita baca. Banyak orang ingin percaya pada keindahan, pada kesempunaan sosok putri tak bercela yang sudah selayaknya dipuja dan dicintai. Dan begitu pula sosok sempurna sang pangeran, eh, putri yang menjadi penyelamat dan meminangnya, lalu mereka berjanji akan setia sehidup semati hidup bahagia selamanya, tanpa pernah selingkuh.
Setiap kali buku ditutup dan membaca dua kata akhirnya the end, saya selalu bertanya, “Sungguhkah berakhir, apa yang terjadi selanjutnya?”
Bagaimana jika setelah mereka menikah, ketahuan bahwa sang putri ternyata punya banyak perempuan simpanan di haremnya dan Cinderella hanyalah salah satu dari koleksinya. Putri yang menyelamatkan Snow White ternyata perempuan dengan hobi seks menyimpang dan buaya kelas berat yang tidur dengan banyak orang, secara mana ada sih orang yang kucluk-kucluk cium cewek yang sedang tidur di hutan kecuali pervert gitu? Bagaimana dengan Sleeping Beauty? Ketika sang pangeran, eh putri datang, dengan suka rela dia menyerahkan diri dan kesetiaannya hanya untuk mendapati bahwa sang putri hanya ingin menidurinya demi mencicipi keperawanannya lalu pergi meninggalkannya seorang diri.
Banyak orang yang nggak akan mau membaca cerita itu. Cerita semacam itu pantasnya masuk cerita horor, terlalu mengerikan buat jiwa perempuan kita. Kebanyakan orang menyukai akhir yang bahagia dan kisah yang manis mendayu. Mereka ingin diyakinkan bahwa pada akhirnya sang putri yang miskin tapi cantik, baik budi dan bermoral tinggi akan menikah lalu hidup bahagia selamanya dengan sang pangeran dalam kesetiaan absolut.
Kita mendambakan kesempurnaan, merindukan dunia utopis lesbian di mana segalanya indah. Perempuan bertemu perempuan. Mereka jatuh cinta. Mereka hidup bahagia bersama. Itulah sebabnya mengapa cerita roman model Harlequin laris manis. Jangan heran jika sinetron-sinetron nggak jelas itu tetap punya banyak penonton, karena banyak orang yang memang mendambakan ilusi yang dijual oleh produser TV.
Realitas yang keras dan sering kali menyakitkan membuat banyak manusia, lesbian/straight, menciptakan ilusi kesempunaannya sendiri. Menciptakan sosok-sosok ala dongeng Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, atau tokoh-tokoh lainnya sebagai image yang ditampilkannya. Dan hebatnya, manusia yang menciptakannya sungguh-sungguh percaya pada ilusi ciptaannya sendiri. Karena tanpa ilusi itu, mereka tahu mereka bukanlah apa-apa.
@Alex, RahasiaBulan, 2008
Tulisan ini sudah lama terkatung-katung karena saya patah hati minggu lalu. Berkat dukungan teman-teman semua, kini saya merasa dunia tidaklah sesuram gua gelap seperti di film The Descent. :p
Beberapa minggu lalu saya menonton film berjudul Titanic Town di layar televisi. Ceritanya tentang seorang ibu yang jadi aktivis di kota kecil di Irlandia Utara. Si itu berjuang untuk menghentikan pertikaian antara Inggris dan Irlandia. Walaupun sudah diwanti-wanti agar tidak terlalu vokal, akhirnya si ibu ini malah jadi aktivis yang melakukan kampanye besar-besaran menentang perang antara IRA dan Inggris hingga masuk TV dan koran lalu si ibu itu jadi terkenal. Kemudian anak-anak dan suaminya mendapat ancaman dan teror, rumahnya jadi sasaran pengrusakan, dan keluarganya hidup dalam ketakutan.
Ketika saya menontonnya, saya kasihan dan kesan pada si ibu. Layak nggak sih berjuang sampai sejauh itu? Memang sih nasib ibu itu tidak semalang perempuan yang anaknya diculik, lalu diperkosa dan dibunuh di depan matanya dalam film Imagining Argentina. Ibu itu yang diperankan oleh Emma Thompson adalah pejuang tangguh menghadapi represi pemerintah. Tapi bagi saya, kedua ibu ini adalah ibu egois yang hanya mementingkan diri sendiri.
Apa sih sebenarnya yang mendorong mereka berjuang? Alasan yang mereka pakai adalah mereka berjuang demi masa depan anak-anak mereka agar bisa hidup lebih baik. Yeah, right. Whatever deh.
Di mata saya mereka berjuang karena perjuangan membawa kemahsyuran. Kemasyuran yang berubah jadi candu. Dan membuat buta. Kadang-kadang orang jadi tidak melihat sisi lain karena terlalu fokus pada perjuangan. Mereka marah saat orang-orang tidak ikut berjuang. Merasa dunia seharusnya berputar di sekitar mereka. Mempertanyakan kenapa orang tidak ikut berjuang bersama mereka. Dan yang paling miris, mereka membuat orang-orang yang dekat dengan mereka sebagai korban.
Yeah, kadang-kadang perjuangan itu menghasilkan kemenangan sesaat, tapi dengan harga yang mahal. Anak perempuan dalam Imagining Argentina mati mengenaskan. Anak lelaki dalam Titanic Town kepalanya bocor hingga nyaris mati. Yang lebih miris, perjuangan mereka dimanfaatkan, dijadikan kendaraan politik oleh oknum-oknum politisi atau mereka yang ingin mencari nama dan uang. Pejuang-pejuang itu cuma dijadikan pion tidak penting yang bisa dikorbankan.
Jadi kita tidak harus berjuang? Tidak juga. Berjuanglah secara cerdas. Jangan pernah jadi martir. Jangan pernah berpikir bahwa berjuang sama artinya dengan mengorbankan diri. Saat kau mati, kau mati. Saat keluargamu hidup dalam ketakutan karena teror, kau jadi orang yang bertanggung jawab sebagai penyebabnya. Tidak ada perjuangan yang terlalu penting hingga harus membuat orang-orang di dekatmu menderita.
Yang lebih ironis lagi, setelah kau mati-matian berjuang kau harus pergi dari tempat yang kauperjuangkan karena kau ternyata menciptakan lebih banyak musuh. Lupakan perjuangan, kecuali kau tahu kau akan menang. Segala sesuatu akan terjadi jika waktunya pas. Matahari akan terbit saat fajar. Bintang bersinar di malam hari.
Saya lupa siapa, tapi ada yang pernah bilang bahwa coming out sebagai lesbian adalah suatu bentuk perjuangan kita sebagai lesbian. Rahang saya sampai nyaris copot mendengar komentar itu. Yang lebih bodoh lagi adalah ajakan/hasutan untuk coming out. Saya yakin, tanpa diajak pun, setiap lesbian merasakan kegelisahan untuk out.
Been there, done that.
Saya melewati masa muda yang penuh kegelisahan. Rasanya saya ingin menjerit di puncak gunung tertingi dan menyatakan diri sebagai lesbian. Mengaku kepada ibu saya tinggal seujung kuku lagi ketika saya masih duduk di bangku kuliah. Tapi saya tidak melakukannya ketika saya masih muda dulu, walaupun hati saya sakit karena harus memendam perasaan. Ya, akhirnya memang saya out ketika saya merasa waktunya tepat dan orang-orang pasti bisa menerima kelesbianan saya. Saya tidak mau jadi pecundang yang cuma bisa mengaku lesbian dan menjadikan lesbian sebagai identitas. Meminjam istilah Nagabonar, Apa kata dunia?
Ada orang yang sepenuhnya in the closet. Ada yang memilih out di kalangan sesama lesbian. Ada yang memilih out di lingkungan kerja saja. ada orang yang memilih out di lingkungan keluarga saja. Ada orang yang sebegitu out-nya sehingga identitasnya cuma si anu yang lesbian. Itu semua hak masing-masing. Terserah di mana letak kenyamanan orang tersebut. Apa yang bagus buatmu belum tentu bagus buat orang lain. Kau tidak pernah bisa menempatkan hidupmu dan penerimaan terhadap dirimu terhadap diri orang lain.
Sebagaimana cerita di atas, jika kau tidak tahan lagi dan ingin out, lakukan secara cerdas. Janganlah melakukannya dengan membabibuta apalagi karena menuruti emosi/amarah. Atau kau melihat si A melakukannya dan tampaknya cool atau ditekan oleh pasangan untuk melakukannya. Lakukan dengan penuh pertimbangan, paling tidak yang bisa kauprediksi bahwa kira-kira orang yang mendengar ceritamu akan bisa mendukungmu. Saya memilih out kepada orang-orang yang sudah saya kenal baik dan tidak kepada keluarga.
Beberapa hari yang lalu ibu saya bilang, “Kamu tuh anak yang baik.” DUK. Secara ibu saya bukan tipe memuji, saya langsung cemas. Dan dengan tatapan gundah, saya balik bertanya, “Mama nggak kenapa-napa, kan?”
Ibu saya malah ketawa terbahak-bahak. “Masa nggak boleh memuji anak sendiri?”
Saya tidak pernah out pada ibu atau keluarga besar saya, karena saya tahu karakter ibu saya yang memilih untuk “Don’t ask don’t tell.” Dia memilih diam dan menerima keadaan saya yang sejak kuliah sering membawa “teman perempuan” ke kamar (kamar saya letaknya persis di sebelah kamar ibu saya yang cuma dibatasi tripleks, jadi bayangkan sendiri deh :p), plus mengajak teman perempuan menginap di rumah, plus pernah tinggal di kos bareng bersama “teman perempuan” dengan ranjang yang kata ibu saya, “Terlalu sempit untuk berdua”. Saya rasa membahas orientasi seksual saya adalah penghinaan buat kecerdasan ibu saya. Kemudian ibu saya memotong lamunan saya dan berkata, “Mami lagi banyak duit nih. Gimana kalau hari Minggu kita makan siang di luar? Oya, jangan lupa ajak Lakhsmi sekalian.”
Ah, mendadak saya teringat tulisan entah di mana, "We’re happy, we’re gay." Tolong jangan buat saya merasa bersalah karena merasa bahagia.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Beberapa hari terakhir ini saya bertugas di suatu tempat di luar Indonesia. Bersama beberapa rekan sekantor, saya harus menghadiri event besar tahunan tempat saya bekerja. Walaupun kadang-kadang saya tidak merasa di luar negeri karena sepanjang hari terperangkap dalam ruangan di antara satu meeting dan meeting lain dan sarapannya tetap nasi. :)
Eniwei, di antara jeda meeting, bos saya mendadak berkomentar, "Abis ini kita meeting sama orang-orang X. Kayanya orang-orang X lesbi semua deh." Saya langsung ketawa kecil mendengarnya. Kemudian saya melongokkan kepala melihat orang-orang X yang dimaksudnya. Ada dua perempuan bule di sana. Yang satu berambut pendek cepak, satu lagi berambut sebahu.
Seakan membaca pikiran saya, mbak bos berkomentar, "Yang pirang cepak itu kayanya lesbi deh. Yang satu lagi aku nggak tau, nggak pernah ketemu. Tapi yang dulu juga modelnya sama seperti itu." Kembali saya memanjang-manjangkan leher melihat perempuan itu. Dan gara-gara komentar bos saya itu, pas meeting bukannya konsentrasi, saya malah ngeliatin perempuan itu. Halah, bener-bener ngawur deh.
Untungnya sengawur apa pun saya, meeting berlangsung lancar. Kemudian bos saya berkomentar, "Di sini kebanyakan perempuan ya?" Saya kembali menoleh ke kiri-kanan melihat sekeliling dan mendapati memang mayoritas peserta dan orang-orang yang kami temui adalah perempuan. Termasuk kami.
Sudah lama saya menyadari bahwa perempuan memang memegang peran mayoritas dalam bidang pekerjaan yang saya geluti. Bukan bermaksud sexist, tapi saya paham laki-laki akan sulit mengerjakan bidang pekerjaan ini karena selain target market kami memang mayoritas perempuan, pekerjaan ini membutuhkan naluri dan kepekaan yang besar dalam urusan perasaan. Dan dalam hal ini saya setuju sekali bahwa
Men are From Mars and Women are from Venus.
Balik lagi ke isu lesbian.
Setelah menghabiskan malam-malam di hotel bersama rekan kerja, saya mendapati kami menjalani keakraban lebih daripada keakraban yang kami peroleh jika hanya bertemu di kantor. Plus ditambah penerbangan belasan jam yang membuat kami jadi makin akrab. Dari sana saya memperoleh banyak pelajaran berharga. Saya belajar bagaimana rekan-rekan kerja saya yang hetero memandang saya sebagai lesbian. Bagaimana tanggapan mereka terhadap diri saya, bagaimana penerimaan mereka terhadap saya.
Bukan masalah besar, sebenarnya. Hanya hal-hal kecil yang membuat nyaman. Hal-hal kecil seperti peristiwa di atas, pertanyaan-pertanyaan seperti, “Gimana kabar Lakhsmi?” atau “Sudah berapa lama sama dia?” Atau ketika SMS masuk, rekan kerja bertanya, “Lakhsmi ya?” Atau seorang rekan kerja bercerita tentang hubungannya dan kami berakhir dengan saling cerita tentang kehidupan cinta kami masing-masing. Mereka tidak memandang saya “beda” atau “lebih” atau “kurang”.
Beberapa hari bersama kolega dan rekan kerja itu membuat kami berada dalam satu melting pot. Saya merasa terjalinnya keakraban lepas batas dan lumernya perbedaan dalam belanga persahabatan adalah kelebihan istimewa yang tak dapat digantikan oleh aneka hubungan persahabatan yang lain.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Peringatan: *nggak usah dibaca deh, ini cuma tulisan ngawur yg dibuat saat moody*
Akhir pekan kemarin saya makan siang dengan seorang sahabat SMA. Seperti biasa, bila sudah bertemu dengannya, kami selalu me-recharge diri kami dengan obrolan intelek dan cerdas ala perempuan. “Lo tau nggak sih betapa pentingnya surat nikah dan pernikahan?” Tiba-tiba Cindy bertanya. Belum sempat saya menjawab, dia sudah melanjutkan, “Gue udah bertahun-tahun pacaran sama sama suami orang. Belakangan ini gue sadar, secinta-cintanya dia sama gue, dia nggak akan meninggalkan istrinya. Legalitas pernikahan itu adalah tali komitmen yang tak kasatmata.” Terkadang ada hari-hari tertentu ketika Cindy amat bijaksana.
Saya teringat sahabat saya yang lain, yang sudah 7 tahun jadi “istri” pria beristri. Saya pernah menanyakan keseriusan si pria yang jadi pasangannya, dan si pria itu berkata dengan sok bijak, “Yah, kamu tau kan posisi saya gimana? Saya kan udah beristri. Dan saya Katolik, jadi saya tidak bisa bercerai dengan mudah. Sahabat kamu mestinya ngerti ini.” Pada saat itu saya ingin bangun dari sofa dan meludahi laki-laki bajingan itu. Bukan karena dia selingkuh, tapi karena caranya memanfaatkan agama sebagai tameng. Bersikaplah jantan, dan katakan, “Saya tidak akan meninggalkan istri saya. Kalau masih mau, mari kita jalani hubungan ini. Dan jangan tuntut macam-macam dari saya.” Nggak usah deh pakai janji-janji gombal. Nah kalau habis itu sahabat saya masih mau dengannya... silakan jalani hubungan itu dengan lapang dada.
“Sekarang nih ya, gue sih berusaha menghilangkan cinta itu dari hati gue. Buat apa?” Cindy melanjutkan. “Gue akan selalu jadi orang luar yang melihat ke dalam. Daripada sakit hati lebih baik gue menghapus rasa cinta itu. Apalagi doi udah punya anak. Gue tuh cuma urutan kesekian dalam hidupnya. Dia bilang dia udah nggak cinta lagi sama istrinya. Dia cuma mikirin anak-anaknya. Gue sih dulu bego ya, masih berharap muluk tentang ‘cinta akan mengalahkan segalanya’. But, my dear friend, itu cuma laris buat jadi bahan novel atau film. Kalau misalnya ada orang yang meninggalkan pasangannya demi orang lain, biasanya itu terjadi karena pasangan itu emang sudah bermasalah. Jangan mikir bahwa lo tuh begitu spesialnya bahwa dia akan meninggalkan kestabilannya demi elo. Dan jika dia meninggalkan keluarganya demi orang ketiga, elo akan dikutuk oleh 90% rakyat Indonesia. Liat aja Mayang-Bambang-Halimah. Berapa banyak sih orang yang bilang bahwa Bambang lelaki hebat karena mau bercerai dengan istrinya demi bisa sama Mayang? Paling sering yang muncul adalah, ‘dasar perempuan lonte, bisanya ngerebut laki orang.’”
Hm, gawat nih. Cindy sedang sinis. Saya berusaha jadi pendengar yang baik. Saya tidak pernah menganggap pentingnya legalitas pernikahan... sampai saat itu.
Mendadak saya sedih. Sedih, karena sebagai lesbian (di Indonesia) entah kapan saya mendapatkan tali komitmen yang tak kasatmata itu. Memang, saya tahu banyak orang yang meremehkan pentingnya lembaga pernikahan. Bagaimana kesucian pernikahan sudah dinodai banyak hal, terutama oleh perselingkuhan. Saya pernah menulis bahwa legalitas pernikahan itu tidak penting, yang penting adalah komitmen dalam hati. Saya tarik lagi kata-kata itu. Kertas tak penting yang bernama surat kawin itu ternyata begitu mengikat. Seperti cap darah yang tidak bisa dengan mudah dikesampingkan begitu saja.
Ada beberapa lesbian yang menyatakan pentingnya legalitas adalah untuk warisan bila salah satu pasangan meninggal. Buat saya, itu alasan yang tak masuk akal saya, karena kita bisa punya banyak cara untuk perlindungan semacam itu. Alasan utama yang terlupakan atau terkadang taken for granted adalah kemampuan surat nikah membuat ikatan yang bisa membuat lesbian memiliki tempat bernaung, tujuan pulang... dan terutama punya tujuan dari hubungan. Bukannya seperti sekarang, ketika banyak pasangan lesbian dengan mudah angkat koper meninggalkan pasangan kita walaupun “katanya” sudah ada komitmen.
Sewaktu saya berumur 20-an, saya merasa tidak peduli sama apa yang namanya surat kawin. Dengan sinis saya menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh dan nggak ngerti kenapa sih orang membesar-besarkan masalah pernikahan. Apalagi karena saya lesbian, jadilah saya orang yang makin sinis. Daripada sakit hati, lebih baik sinis dulu, kan? Seperti kata Scott Turow, “in a body of a cynic, beats a broken heart of a romantic.”
Sekarang terserah deh kalau orang lain tidak menganggap pernikahan penting. Terserah deh kalau saya dibilang kuno. Terserah deh kalau saya dibilang nggak cool. Terserah deh kalau saya dibilang rese. Saya tidak peduli.... saya ingin diikat oleh tali tak kasatmata itu.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Beberapa orang pernah bertanya kenapa saya tidak meresensi buku lesbi berjudul anu atau itu. Dari pertanyaan-pertanyaan itu memang ada yang bukunya belum saya baca. Namun ada juga buku yang pernah saya baca, tetapi begitu jeleknya hingga tidak bisa saya resensi di sini karena saya tidak mau membuat blog ini jadi tempat sampah unek-unek kekesalan saya.
Dulu, dalam masa sebelum blog ini muncul saya pernah meresensi satu buku lesbian yang saya edarkan di milis dan diupload di sebuah situs lesbian, yang habis saya cabik-cabik hingga tetesan terakhir. Puaskah saya? Tidak. Saya makin marah dan kesal setiap kali membaca review itu
Dunia pun berputar lalu saya bersahabat dekat dengan seorang penulis yang menerbitkan buku bertema gay. Di mata saya, buku itu begitu bagus. Kemudian buku itu dibantai habis di sebuah media nasional sampai setengah halaman koran, hingga saya dan sang penulis bingung, kenapa sih ada orang bisa sejahat itu? Well, bukunya memang tidak sampai jadi masterpiece atau buku sempurna, tapi tetap saja tidak layak diperlakukan sekeji itu.
Dua kejadian ini membuat saya belajar banyak tentang selera pembaca. Bagaimana satu karya yang dilemparkan ke ruang publik menjadi satu karya yang bisa menimbulkan multitafsir. Bagaimana sesuatu yang dianggap bagus, bisa dianggap sebagai telur busuk oleh orang lain. Demikian pula sebaliknya. Saya sadar saya tidak bisa memaksakan kehendak dan pendapat saya terhadap satu karya agar orang juga ikutan sependapat dengan saya, karena selera itu amat berbeda sesuai pribadi masing-masing.
Bagaimana seseorang menilai suatu karya dipengaruhi oleh banyak hal. Bagaimana cara dia dibesarkan, masa lalunya, hobinya, lingkungannya, dll. Saya adalah pecinta buku fiksi dan belajar banyak dari buku-buku itu. Saya dibesarkan oleh buku-buku Mira W., Sidney Sheldon, Lima Sekawan, HC. Andersen dari perpustakaan sekolah. Semasa remaja saya menggali jiwa feminis saya bersama buku Nawal El-Sadawi dan Louisa May Alcott, belajar memberontak bersama JD. Salinger, dan perih bersama buku Elie Weisel. Tanpa melupakan cinta lama, saat ini saya sedang belajar mencintai buku remaja dan komik novel grafis, Neil Gaiman, Frank Miller, Alan Moore, dll.
Kini tidak ada satu hari pun yang saya lewatkan tanpa membaca dan saya masih terus haus mencari bacaan bagus, terutama fiksi. Saya jatuh cinta pada buku fiksi karena kemampuannya membuat saya belajar, terpukau, tertawa, atau menangis. Uniknya, saya hanya punya sedikit koleksi buku---mungkin jumlahnya cuma seratusan yang saya anggap personal best---karena sering kali selesai membaca saya memberikan buku itu buat orang lain supaya ikut merasakan bahagia yang saya rasakan.
Itu pula salah satu tujuan dari blog ini, berbagi kebahagiaan yang saya rasakan ketika membaca buku yang mengandung unsur LGBT yang membuat perasaan saya meluap-luap. Bukan berbagi kebencian terhadap satu karya. Saya tidak ingin membagi keburukan atau kekesalan di sini, tapi berusaha membagi kebaikan. Tolong ingatkan saya pada postingan ini jika seandainya suatu hari saya lupa dan marah.
Yang harus diasah adalah kemampuan pembaca memilah mana buku bagus dan mana buku jelek (paling tidak untuk dirinya sendiri). Dan saya tidak mau jadi penentunya, karena bisa saja selera kita berbeda, kan? Tapi saya yakin buku yang bagus akan bertahan abadi, dan menyentuh hati banyak pembacanya. Mengutip perkataan seorang sahabat baik saya, “Buku yang bagus akan menemukan pembacanya sendiri.” Blog ini berupaya menjadi penunjuk jalan dan sisanya adalah kehendak bebas pembaca yang membaca resensi buku di sini.
@Alex, Rahasia Bulan, 2007
Pada suatu hari Minggu saya bersama seorang sahabat janjian ketemuan di Grand Indonesia. Setelah berakrobat dengan waktu akhirnya kami janjian ketemu jam 2 siang di sana. Namun ternyata sahabat saya itu, hm, sebut saja namanya Jean, mengajak dua orang biksu dari Tibet....
Di mal supergede itu, saya dan Jean berjalan bersama dua biksu yang mengenakan jubah lengkap mereka yang mencolok mata. Jadi bisa kebayang kan bagaimana saya seperti cacing kena abu, tidak merasa nyaman saat ribuan mata memandangi kami... (well, ini cuma hiperbola, karena puluhan mata itu rasanya seperti ribuan). Saya perhatikan Jean tampak biasa-biasa saja... maklum dia dan biksu-biksu ini sering keluar ke tempat umum bersama, tidak seperti saya. Akhirnya, tidak tahan saya berbisik pada Jean, “Emang biasa diliatin gini ya?”
“Iya,” jawab Jean mengangguk.
“Elo nggak risi?”
“Jangan dipikirin, cuek aja lagi,” tukasnya sambil mengajak kami masuk ke Food Hall.
Mendadak saya jadi teringat cerita seorang sahabat lain, kali ini sahabat lesbian. Dia bercerita betapa dia merasa semua mata memandanginya saat dia jalan bersama kekasihnya di tempat umum. Dulu pas denger cerita itu sih saya pikir si sahabat lesbian ini, hm, sebut saja namanya Mon, mungkin menunjukkan afeksi berlebihan di depan umum sehingga “dilihatin” orang-orang. Tapi mereka bilang, mereka cuma pegangan tangan kok. Waktu itu saya jawab padanya, “agh, gue sih nggak pernah merasa diliatin gitu... perasaan elo aja, kali.” Mungkin, ternyata selama ini dengan atau tanpa saya sadari saya merasa nyaman pada diri saya sendiri sehingga tidak merasa salting saat berjalan di depan umum dengan partner. "Teori" itulah yang baru saya sadari saat saya dihujani tatapan orang-orang siang itu.
Saat saya dipandangi orang satu mal segede gaban itu, bahkan setelahnya kami berjalan kaki ke Plasa Indonesia, saya mengerti apa yang dialami Mon. Saya merasa tidak nyaman, gelisah, risi, dll. Saya jadi merasa salah tingkah alias self-concious. Pertama-tama muncul perasaan defensif, “Kenapa sih pada ngeliatin? Nggak pernah liat biksu jalan-jalan di mal ya?” Namun setelah saya melihat Jean bisa dengan santai mengobrol dan berjalan dengan cuek, saya jadi mikir, “Well, mungkin cuek is the best ya?” Cuek di sini maksudnya bukan cuek tetap leha-leha di tempat tidur saat banjir melanda, atau cuek ketika api mulai melahap rumah sebelah. Lalu mulailah saya membuat diri saya cuek, dan terutama berhenti memikirkan pendapat orang lain tentang diri saya. Akhirnya saya pun bisa berjalan bersama dan mengobrol dengan Jean dan biksu-biksu itu tanpa merasa salah tingkah.
Saya jadi teringat cerita komik Buddha karya Ozamu Tezuka, dalam seri ke-4 ketika Siddharta bertapa di Hutan Uruvela, ada seorang bocah ingusan (bocah ini benar-benar ingusan) yang sudah ditakdirkan mati pada umur tertentu. Namun bocah ini tampak tenang menghadapi kematiannya, dan ketika Siddharta yang kala itu belum menjadi Buddha bertanya pada bocah itu apa resepnya tidak takut menghadapi kematian, si bocah menjawab, “Cuek aja, lagi.” Yeah, betul juga. Terlalu mengkuatirkan sesuatu membuat kita malah tidak fokus pada sesuatu yang penting, yaitu hidup itu sendiri.
Mungkin itulah yang harus kita rasakan sebagai lesbian. Coming out atau tidak, kita harus nyaman pada diri kita sendiri. Tahu apa yang kita mau dan berkonsentrasi pada hal itu, bukannya berkonsentrasi pada, "Orang-orang bilang apa ya tentang gue?" Sekali lagi, maksudnya nyaman bukan nyaman saat jalan rame-rame bergerombol bersama lesbi lain dan caper (cari perhatian) di mal atau tempat umum ya. Tapi lebih ke nyaman pada diri sendiri, nyaman menjadi diri sendiri... apa pun bentuk, wujud, dan rupa kita. Bukan kepada diri lesbian kita saja, tapi juga kepada diri manusia kita seutuhnya. Percayalah, dengan ini penampilan Anda akan lebih berbinar dan menarik perhatian sesama jenis. (baca dengan suara ala iklan pemutih wajah :p)
Well, keesokan paginya saya tiba di kantor, dengan penampilan ala saya. Rambut awut-awutan, belum dandan, mata masih ngantuk---maklum, karena belum bangun kalau belum keseduh kopi, teman kerja saya langsung bilang, “Stop! Jangan bergerak!” Tangannya mengeluarkan ponsel berkamera.
Waks, saya pun kaget, buru-buru menghindar, “Ngapain sih mau motret gue?” Masih dengan rasa tidak nyaman, dalam hati berkomentar, Maksud lo?
“Udah, lu diem jangan bergerak deh. Gue mesti mengabadikan elo seperti ini, nanti gue post di blog gue dengan judul, 'Orang Paling Cuek Sedunia.'" Hhhh... :(
@Alex, Rahasia Bulan, 2007
Bagian I
Di antara kalian berdua, siapa yang jadi cowoknya?
Hayo, seberapa sering pertanyaan semacam itu kita dengar? Saya, yang bekerja di lingkungan yang didominasi perempuan, dan menjalin persahabatan dengan banyak perempuan hetero sampai hanya bisa memutar bola mata setiap kali mendengar pertanyaan seperti itu. Entah mengapa, konsep hubungan tanpa peran lelaki itu membuat mereka bingung, dan dalam pikiran mereka juga, lesbian yang cewek banget harus menjalin hubungan dengan lesbian macho bak laki-laki.
Biasanya pertanyaan itu hanya saya jawab dengan senyum manis, dan, “Mbak, ini nggak ada cowoknya gitu lho... dua-duanya cewek.”
Biasanya ada yang langsung menelan jawaban itu, namun ada pula yang keukeuh bertanya, “Bukannya ada tuh lesbi yang cowok banget? Yang kayak laki?” Hm, mulailah saya, yang tadinya enggan, memberi penjelasan panjang-lebar soal butch, femme, dan andro dalam hubungan lesbian. Halah, ternyata penjelasan saya itu membuat mereka jadi tambah yakin tentang pembagian peran laki-perempuan dalam hubungan lesbian. Waks, ternyata salah nih, mungkin tidak seharusnya saya cerita tentang butch, femme, dsb itu. Hhhh... aku dan mulut besarku :p
Hm, akhirnya setelah capek ngasih keterangan yang makin lama makin nggak jelas, saya bertanya, "Mau gue pinjemin film-film L gue nggak?"
"Bokep ya?" tanya teman saya dengan wajah jijik.
"Bukanlah, (plis deh, emangnya cewek apaan?) film drama lesbian biasa. Elo nonton aja deh, ambil kesimpulan sendiri. Pusing gue nerangin soal ini."
Akhirnya sahabat saya itu jadi satu sahabat yang rajin meminjam film-film saya... banyak film yang pernah diresensi di blog ini sudah dia tonton, bahkan ikutan milis The L Word... dasar gokil tuh cewek :).
Hhh, mendadak ingat The L Word season 2 saya dipinjam siapa ya?
Bagian 2
Bagaimana sih caranya? Well, sebenarnya sih ini pertanyaan yang juga muncul di benak lelaki hetero bahkan lelaki gay. Bagaimana caranya lesbian melakukan hubungan? Emangnya bisa menikmati hubungan tanpa “itu”--- "itu" maksudnya alat kelamin lelaki---? Atau beragam pertanyaan turunannya. Buat saya, jawaban, “Sini deh, gue praktekin,” adalah jawaban basi basi banget.
Biasanya kalau mendapat pertanyaan itu, saya menampilkan senyum semanis mungkin lalu saya menjawab dengan wajah prihatin, “Wah, lo kasian sekali ya nggak ngerti tentang konsep orgasme pada tubuh perempuan.” Lalu saya beri penjelasan panjang-lebar tentang orgasme klitoris, orgasme vaginal. Bagaimana tubuh perempuan itu begitu ajaibnya sehingga kita diberkahi klitoris yang gunanya cuma satu, yaitu menjadi pusat kenikmatan buat perempuan.
“Ah, elo belum pernah coba sih, jadi nggak tau enaknya sama lelaki,” timpal sahabat saya sambil cekikikan.
“Sapa bilang nggak pernah coba? Sebelum memutuskan suka burger atau tempe, harus coba dua-duanya dong,” sahut saya.
Sahabat saya kaget, dan bertanya lagi. “Lha emangnya lo pernah sama lelaki?”
Hihihi, saya hanya cengengesan dan berlalu tanpa menjawab.
Bagian 3
“Emang lo pernah disakitin laki-laki ya sehingga jadi lesbian?”
Haduh, gubrak, bletak... Pertanyaan ini tahun 90-an banget sih? Jadoel gitu lho, Sis! (maksudnys Sis di sini sister, bukan Siska :p) Huaaaaaaaaah. Jadi inget cerita-cerita di rubrik "Oh Mama Oh Papa" geto, “Aku Jadi Lesbian Karena Dikhianati Lelaki.” Halah.... plis deh.
“Sis, tau nggak sih, justru aku yang menyakiti laki-laki sampai bercucuran air mata terakhir kali putus ama laki.”
“Kamu belum ketemu lelaki yang baik, kali?” Dilanjutkan dengan ceramah sahabat saya bahwa di dunia ini masih banyak lelaki baik, tidak semua lelaki bajingan, dll... blablabla, yatayatayata...
“Duh, gini lho, mbak, eh, sis..., aku tuh nggak ada masalah sama lelaki.”
Sahabat saya itu memandang heran, di matanya terungkap pertanyaan yang tak ditanyakannya, Kalau nggak ada masalah, kok nggak sama laki aja?
Saya pun melanjutkan, menjawab pertanyaan tak terucapkan itu. “Gini lho, sis, aku tuh nggak benci atau sakit hati sama lelaki. Tapi masalahnya adalah ketidakmampuanku membayangkan hidup bersama lelaki. Eits, bukan soal seksnya... karena mekanismenya tidak ada masalah buatku. Tapi membayangkan diriku pulang ke rumah, pulang ke lelaki, itu yang tak pernah bisa membuatku nyaman dan bahagia.”
Melihat Si Sis ini masih bingung, saya lanjutkan, “Seperti kamu dan suamimu. Bagaimana kamu bahagia bisa berbagi bersama suamimu. Melakukan hal-hal yang mungkin sepele. Nonton TV, makan, pijat-pijatan, atau apalah. Pulang kerja ke rumah, menunggunya atau ditunggu olehnya... rasanya klop, kan? Rasanya at home? Nah itu yang hanya bisa aku rasakan dengan perempuan.”
Lalu sahabat saya mengangguk-ngangguk, entah mengerti atau tidak. Kalau dia masih bertanya lagi, biar nanti saya pinjami dia DVD The L Word atau film-film lesbian lain yang saya punya. :)
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Tidak, saya tidak ingin menulis resensi buku terjemahan bahasa Indonesia berjudul The Secret karangan Rhonda Byrne yang bestseller di mana-mana. Tapi tulisan ini memang terinspirasi dari buku tersebut. Konon, pikiran positif akan menarik hal yang positif demikian pula pikiran negatif akan menarik hal negatif. Saya selalu percaya bahwa pikiranmu adalah yang menjadi surga atau nerakamu di bumi. Berpikir positif akan membuat kita sehat dan bahagia, sementara pikiran negatif aku memakanmu pelan-pelan seperti parasit. Merasa bahwa diri merupakan makhluk paling menderita di muka bumi ini dan mengeluh tanpa henti tentang betapa naas hidupnya bisa dipastikan itulah realitas yang terus-menerus terjadi padanya bak lingkaran setan.
Ah, izinkan saya bercerita tentang perjalanan hidup seorang perempuan. Alkisah, ada seorang perempuan, yang setamat sekolah menengah tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi karena pada zamannya perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena pada akhirnya dia hanya perlu jadi istri dan ibu rumah tangga. Padahal dia punya kecerdasan dan potensi untuk meneruskan sekolah. Akhirnya perempuan itu pun menikah, yang untuk ukuran zamannya termasuk telat menikah. Bersama suaminya yang tampan namun mata keranjang, ia punya lima anak.
Hidupnya mengalir terus hingga mendekati setengah abad, dan suaminya meninggal, meninggalkan anak bungsu berusia 5 tahun dan anak kedua yang terpaksa tidak bisa kuliah karena keluarganya bisa dibilang bangkrut karena habis membiayai pengobatan almarhum suaminya yang menderita kanker. Untuk pertama kalinya saya melihat perempuan itu menangis ketika suaminya meninggal. Tapi ketika masa berkabung selesai, tangisannya berhenti dan hidupnya berlanjut. Dia tidak menganggap hidup tidak adil atau mengeluh pada semua orang tentang betapa menderita dirinya yang harus menjadi janda.
Untuk membiayai kebutuhan keluarga perempuan setengah baya ini harus kembali lagi masuk ke dunia kerja, apalagi karena salah seorang anaknya bersekolah di SLB yang biayanya cukup besar kala itu. Lalu perlahan-lahan hidupnya membaik, dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka usaha sendiri di rumah. Tiap hari bangun pukul 4 pagi, menyiapkan makanan untuk dijual, tapi menurutnya itu masih lebih baik daripada harus pergi bekerja ke luar rumah. Tidak ada satu hari pun dia merasa hidupnya menderita, tiap hari di rumahnya selalu ada tawa dan keramaian walaupun tidur beralaskan tikar.
Tidak pernah sekali pun saya mendengar keluhan terdengar dari mulutnya. Mengeluh capek pun tidak pernah. Bahkan saat kanker menyerangnya ketika usianya mendekati 70 tahun pun, dia menghadapinya dengan tenang. Tidak ada rasa takut mati saat dia didiagnosis menderita kanker. Ketika satu payudaranya harus diangkat akibat masektomi pun dia tetap berpikir positif. Sudah tua tidak perlu dua payudara lagi, itu katanya berusaha santai. Di rumah sakit dia jadi pasien favorit suster-suster di sana karena selalu ceria dan diajak jadi "motivator" pasien-pasien kanker lain. Bahkan pengobatan pasca-operasi yang melelahkan pun dilewatinya bak angin lalu dan tawa. Lima tahun lebih sejak dia diagnosis kanker payudara, dan sudah hampir lima tahun pula dia dinyatakan bersih dari kanker.
Cobaan untuknya ternyata belum berakhir, karena beberapa tahun lalu anak pertamanya meninggal dunia secara mendadak. Dia menangis, tapi tidak mengeluh dan bertanya kenapa Tuhan memperlakukannya tidak adil. Dia tidak pernah bertanya kenapa hidupnya tidak bisa “seenak” orang lain. Rumahnya selalu jadi “rumah singgah” orang-orang yang di mata orang lain loser. Tapi buat perempuan itu dia belajar bahwa hidupnya masih lebih beruntung dibanding orang-orang lain. Bukannya marah dengan rumah kontrakan yang bocor dan retak-retak, putra kesayangannya diambil Tuhan, atau menganggap anaknya tidak berbakti padanya, dia bersyukur setiap hari karena masih punya tempat bernaung, kesehatan yang baik walaupun tidak sempuna, dan makanan setiap hari.
Setiap hari seumur hidup saya, saya melihat perempuan yang juga ibu saya tersebut menjalani hari demi hari dengan pikiran positif. Sebut saja pepatah "Banyak Jalan Menuju Roma", "Semua Terjadi Karena Ada Alasannya." "Masih Ada Cahaya di Ujung Terowongan." dsb, itulah karakter ibu saya. Yah, ibu saya bukan manusia yang tak pernah salah dan tanpa cela, tapi dia adalah manusia yang paling berpikiran positif yang saya kenal. Saya kagum dengan kemampuannya untuk berpikir positif dan terus belajar... duh, ada berapa nenek-nenek sih yang minta diajari chatting dan video call?
Saya melihat bagaimana pikiran positif ibu saya itu menghasilkan mukzijat-mukzijat yang tak pernah terbayangkan. Uang masuk kuliah saya didapat dengan cara yang begitu ajaibnya hingga sampai sekarang saya sering merasa itu benar-benar hasil dari dukungan alam semesta berkat keinginan positif dan kuat kami berdua (udah bener-bener seperti sinetron deh...). Pekerjaan yang sekarang saya geluti merupakan pekerjaan impian saya sejak SMA, meskipun saya menghabiskan dua tahun setelah lulus kuliah jadi “pengangguran” demi memuluskan jalan memperoleh pekerjaan itu. Saya sadar jika dua tahun itu saya hanya menempatkan diri saya dalam kubang derita, mengasihani diri sendiri, dan tanpa mau belajar, pekerjaan itu takkan pernah saya dapatkan sampai sekarang.
Menjadi lesbian pun tidak pernah membuat saya meratap dan mengais-ngais derita buat diri saya sendiri. Saya tidak pernah merasa terbuang, terpinggirkan, terhina sebagai lesbian. Seperti yang saya katakan pada seorang sahabat baru saya, "Saya menolak 'menciptakan' neraka dalam hidup saya saat ini dengan membiarkan diri saya tidak bahagia dan jadi manusia yang tidak sehat dengan memandang diri saya secara negatif."
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Akhir pekan saya bertemu dengan seorang sahabat lesbian yang wajahnya memancarkan after-glow sex yang berbinar terang. Kebahagiaan tampak jelas di wajahnya. Dalam hati saya berpikir, after-glow ini pasti bukan sekadar seks atau orgasme multipel, pasti ada limpahan cinta mahadasyat antara sahabat saya dan partnernya yang sudah menjalin hubungan selama tujuh tahun hingga membuat dia bisa bercahaya seperti itu. Ah, kok saya merasa seperti jadi Carrie Bradshaw di Sex and the City ya?
Saya percaya bahwa hubungan seks yang sehat dengan partner yang kita cintai akan membuat tubuh dan jiwa makin bugar dan segar. Para pakar seks (maksudnya pakar di sini bukan pelaku aktif ya, melainkan ilmuwan gitu) menyatakan bahwa kegiatan seks dengan orgasme secara teratur bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya; sakit kepala, stres, susah tidur, atau memperlancar peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, bahkan mengurangi risiko kanker, dll.
Kenapa bisa demikian? Karena setiap kali orgasme tubuh melepaskan hormon oxytocin. Dan riset membuktikan peningkatan jumlah oxytocin dalam tubuh bisa mengilangkan sakit/nyeri, sakit kepala, keram PMS atau saat menstruasi, dan nyeri tubuh ringan lainnya. Makanya jika Anda flu atau sakit kepala ringan, jangan langsung beli obat di apotek, cobalah mengajak pasangan Anda untuk “mengobati”nya lebih dulu. Lho, tapi bagaimana jika partner tidak available saat dibutuhkan? Tenang aja.... masih ada yang namanya masturbasi.
Bagi saya sah-sah saja jika seseorang yang sudah punya partner lalu melakukan masturbasi. Perempuan yang orgasme secara teratur bersama partnernya maupun masturbasi biasanya lebih bahagia dan tidak mudah berselingkuh dari pasangannya. Lagi pula, tidak setiap saat partner available untuk jadi “mesin seks” Anda, kan? Masturbasi adalah cara yang sehat, gratis, dan aman buat perempuan untuk memperoleh orgasme. Kenapa? Seperti yang saya sebut di atas, oxytocin yang terlepas setiap kali terjadi orgasme, membuat tubuh rileks, tenang, dan tidur lebih mudah
Banyak mitos yang saya pikir aneh yang membuat seolah-olah masturbasi adalah tindakan “kotor” terutama buat perempuan. Masturbasi bukanlah sekadar fase yang kita lakukan semasa abege atau tidak pantas lagi dilakukan saat kita sudah dewasa dan terutama saat kita sudah punya partner. Lho, memangnya kalau umur bertambah gairah seks juga habis? Masturbasi bukanlah perbuatan orang-orang kesepian yang menyedihkan, tapi tindakan penyaluran kebutuhan seks sehat yang paling aman.
Anggapan bahwa perempuan yang sering melakukan masturbasi adalah bukan “perempuan baik-baik” karena tidak bisa menahan nafsunya adalah anggapan paling konyol yang pernah saya dengar. Lelaki dan perempuan yang normal dan sehat memiliki dorongan seks yang normal dan sehat pula, tapi bagaimana menyalurkannya adalah suatu tindakan yang membutuhkan kedewasaan. Anda bisa menyalurkannya dengan berganti-ganti pasangan, atau bisa dengan masturbasi, bagi saya kedewasaan lebih ditentukan dengan cara itu. Ada juga yang bilang keseringan masturbasi bisa bikin bego, gila, buta, jerawatan, rambut rontok, atau entah apa lagi hal buruk untuk kesehatan. Padahal riset sudah membuktikan bahwa orgasme rutin baik untuk kesehatan... yah, selama dilakukan dalam porsi wajar, karena kalau masturbasi dilakukan tiap hari 3x sehari seperti makan obat sih buat saya udah kelewatan...
Hal terpenting bagi saya adalah masturbasi membantu perempuan mengenali tubuhnya sendiri. Secara teori, perempuan yang tahu bagaimana memuaskan dirinya biasanya juga lebih piawai memuaskan pasangannya, terutama untuk pasangan lesbian. Duh, secara onderdilnya sama gitu lho... Perempuan juga jadi lebih tahu bagaimana cara respons tubuhnya terhadap rangsangan tertentu . Bila sudah demikian, perempuan tersebut akan tahu bagaimana cara melakukan hubungan yang lebih memuaskan dengan pasangannya sehingga hubungan pribadi pun bisa bertahan lama. Mau tidak mau harus diakui bahwa seks memegang peran penting dalam hubungan lesbian.... yah, kalau cuma pegangan tangan aja sih, sama teman juga bisa. :)
Perempuan yang tidak pernah merasakan orgasme biasanya juga tidak memancarkan sex appeal, dan membuatnya tampak tidak menarik dan kusam di hadapan orang lain. Di mata saya, sex appeal bisa terlihat jelas dari perempuan yang memperoleh orgasme secara rutin dan sehat. Ah, seperti kisah awal saya tadi, bagaimana sahabat saya tampak berbinar memancarkan after-glow sex yang dahsyat... saya yakin dia mendapat orgasme secara teratur....
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Bagaimana cara menuangkan kata-kata yang ada di dalam kepala ke dalam tulisan? Bagaimana melanjutkan tulisan yang tak selesai? Bagaimana mengatasi writer's block? Itulah beberapa pertanyaan yang muncul dalam Kongkow Lez yang diadakan oleh IPP pada Sabtu sore 26 Mei 2007.
Ah, saya jadi teringat pada novel saya yang tak pernah selesai. Berbagai tips dari pengarang-pengarang terkenal sudah saya coba, tapi hasilnya nihil. Setiap kali selesai menulis, saya selalu menganggap tulisan saya tidak cukup bagus. Pernah ada satu novel saya yang “nyangkut” sejak tahun 2000, dan ketika saya baca lagi saat ini, saya malah ketawa sendiri membaca tulisan saya yang tak berjiwa itu. Sejujurnya, saya tidak perlu segala tips atau trik dari pengarang-pengarang itu, saya sudah tahu jawabannya. Hingga satu titik saya menyadari bahwa saya bukanlah Jonathan Stroud, dan tidak punya bakat yang cukup besar untuk menjadi penulis fiksi profesional. Saya putuskan untuk menjadi blogger yang baik dan semoga bisa menjadi blogger profesional suatu hari nanti. Maklumlah, saya orang yang percaya bahwa untuk menjadi penulis besar dibutuhkan bakat yang juga besar.
Itulah pernyataan yang tak sempat saya nyatakan dalam Fun with Writing yang diadakan oleh IPP dalam salah satu Kongkow Lez-nya. Acara tersebut dihadiri oleh Cok Sawitri (cerpenis, novelis, dan seniman teater asal Bali), Clara Ng (novelis, cerpenis, penulis buku anak-anak), Is Mujiarso (pengamat sastra), Hetih Rusli (editor). Acara berlangsung fun, seru, dan menyenangkan. Jika gelap belum menjelang, mungkin acara tak juga usai. Saya tidak akan bercerita tentang jalannya acara, untuk itu silakan baca blog sahabat saya, Mumu.
Hari itu saya gembira akhirnya bisa bertemu dengan Cok Sawitri, yang namanya cuma saya pernah saya dengar-dengar sambil lalu. Beberapa hari sebelum acara berlangsung, saya bertanya kiri-kanan siapa sih Cok Sawitri, dan kesimpulannya dia adalah pengarang, penyair, dan pemain teater hebat, dan saya jadi malu karena tidak kenal pada kebesaran nama beliau. Juga Clara Ng, walaupun saya sudah mengenal beliau, dalam beberapa kali acara creative writing bersamanya saya selalu mendapat pelajaran baru darinya. Clara Ng adalah jenis penulis yang haus untuk belajar, di sana saya melihat bagaimana dia membagi ilmu dan belajar bersama.
Dalam setiap acara diskusi creative writing atau how to be a writer, saya selalu mendapat banyak pelajaran untuk menjadikan saya penulis yang baik atau editor yang lebih bijak. Selain “merasa” tidak punya bakat cukup besar untuk menjadi penulis, saya juga tidak bisa menjawab jika ditanya, “Kenapa kamu ingin jadi penulis?” Sejujurnya, saya tidak merasa terpanggil jadi penulis. Tidak ada kegelisahan besar dalam diri saya yang harus saya salurkan melalui tulisan. Cukup melalui media blog, saya sudah puas. Menjadi blogger, memberikan saya kesempatan yang amat besar untuk menuangkan begitu banyak ide yang berkecamuk dalam kepala saya. Menjadi blogger yang anonim memberikan saya keleluasaan yang lebih luas untuk mengekspresikan diri.
Menjelang akhir acara, tampak antusiasme beberapa peserta yang punya niatan menerbitkan novel/karya bertema lesbian. Hm, mungkin saya bisa memberi satu-dua tips dalam hal ini... secara alter ego saya sebagai editor hadir dalam acara Fun with Writing tersebut :p. Agh, cukup sudah novel atau kisah lesbian penuh derita tak berujung. Lebih baik kaukirimkan saja cerita semacam itu ke redaksi “Oh Mama, Oh Papa.” Atau jangan lagi kaujejali pembaca Indonesia dengan cerita pengalaman hidup yang kaupikir ceritamu adalah cerita paling menarik tak ada bandingannya. Cobalah keluar dari kerangkeng itu, buatlah karya yang tak bisa ditolak oleh penerbit saking memukaunya cerita yang kaubuat.
Lihatlah bagaimana penulis sekaliber E. Annie Proulx membuat Brokeback Mountain. Belajarlah dari penulis-penulis luar negeri seperti Julie Anne Peters, Sarah Waters, atau Alison Bechdel, dll, yang karya-karyanya tidak hanya jadi bacaan “khusus lesbian”, tapi bisa diterima umum bahkan memperoleh banyak penghargaan sastra internasional. Atau belajar dari Alberthiene Endah yang membongkar ulang naskah Jangan Beri Aku Narkoba (Detik Terakhir) dari 600 halaman menjadi 248 halaman, yang akhirnya menjadi buku pemenang Adikarya Ikapi 2005. Atau belajar dari perkataan Cok Sawitri, “Gali cerita dari unsur budaya Indonesia.”
Sambil menunggu adanya novel-novel lesbian berkualitas, yang perlu dilakukan saat ini adalah membangkitkan minat baca di kalangan lesbian. Minat baca yang sebesar-besarnya dan secerdas-cerdasnya, agar pernyataan Mumu bahwa lesbian menyukai hal yang bersifat intelektual terbukti benar. Dan jika nanti makin banyak buku bertema lesbian yang terbit, mereka tidak membelinya asal tubruk cuma karena ada unsur lesbiannya walaupun ditulis asal-asalan dan sekadar mencari sensasi.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Setiap kali mendengar kabar putusnya hubungan seorang sahabat lesbian yang sudah menjalin hubungan selama beberapa tahun dengan pasangannya, kesedihan selalu mengaliri pembuluh darah saya. Rasanya ada keseimbangan yang goyah, sesuatu yang saya percayai direnggut begitu saja. Yah, memang saya tidak bisa mengatur hubungan cinta seseorang. Sebagaimana kata seorang sahabat saya, “Sometimes we just fall out of love.” Kita tidak bisa menentukan seberapa lama seseorang harus mencintai dan dengan siapa dia seharusnya jatuh cinta.
Kadang-kadang dalam hubungan kita menemukan cinta yang baru, kadang-kadang cinta terlepas dari genggaman begitu saja. Cinta adalah makhluk paling kompleks yang sama kompleknya dengan manusia itu sendiri. Bahkan konon katanya cinta yang membuat dunia berputar. Seperti kata Martina McBride dalam lagu berjudul Anyway;
You can love someone with all your heart
For all the right reasons
In a moment they can choose to walk away
Love 'em anyway
Tapi ke mana arah cinta lesbian? Apa sih idealnya suatu hubungan lesbian? Legalisasi pernikahan sesama jenis supaya kita punya ikatan yang sah menurut hukum? Ah, kita tidak perlu berpikir semuluk itu. Secarik kertas tidak membuat orang bertahan untuk mencintai. Saya pesimis bukan karena pernikahan sesama jenis tidak mungkin terjadi di sini. Karena pernikahan BUKAN tentang agama. Pernikahan adalah tentang keluarga. Tentang cinta. Tentang komitmen.
Seorang teman hetero yang amat religius, yang jadi tempat curhat saya pertama kali saat coming out dengan bijak berkata, “Elo tuh ya jangan ganti-ganti pacar melulu dong. Itu yang bikin dosa. Mestinya elo cari satu pasangan, lalu berkomitmenlah sama orang itu. Halah, nggak usah mikirin surat kawin. Yang penting dalam hati elo. Orang zaman film silat itu aja nggak pake surat kawin kok. Tinggal tancepin hio, udah deh kawin.” Maafkan analogi sahabat saya yang kebanyakan nonton film silat, namun buat saya kata-katanya begitu mengena.
Menurut saya, masalah utama kehidupan lesbian adalah rasa bosan dan sindrom rumput tetangga tampak lebih hijau. Kita bosan dengan hidup yang begitu-begitu saja. Saat mencapai jangka waktu tertentu dalam hubungan, biasanya hubungan memasuki masa tenang dan kita menjalani rutinitas tertentu. Di sanalah muncul rasa bosan. Saat kita bosan, ada bisikan yang memunculkan ide di kepala kita, “Benarkah dia the one? Soulmate yang kita cari? Bagaimana jika ada seseorang di luar sana yang menungguku?” Atau tanpa sengaja muncul orang baru dalam hati kita yang rasanya lebih seru dan menantang untuk dikejar dibanding kita harus terus terbelenggu dalam pola hidup rutin.
Seperti kata seorang sahabat lesbian saya, “Duh, kok hubungan gue kayaknya gitu-gitu aja ya? Nggak ada tantangannya lagi. Udah lima tahun sih.” Padahal di mata banyak lesbian yang baru menjalin hubungan, hubungan sahabat saya dan partnernya bisa dibilang membuat iri. Bagaimana tidak? Dia dan pasangannya sudah tinggal bareng dan hidup bersama berdua tanpa diutak-atik oleh orangtua. Ya, itu tadi. Rumput tetangga selalu lebih hijau.
Saya tidak bisa memberi nasihat. Saya tidak layak. Saya hanya berusaha menjalani hari demi hari dengan partner saya. Berusaha menjadi partner yang baik, dan setiap kali melihat rumput tetangga yang hijau dan meriah, saya berkata, “Say, akhir minggu ini kita rapiin lagi rumput di depan rumah kita yuk.... Biar subur dan hijau seperti rumput tetangga.”
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Bagian I
Seorang sahabat gay bertanya pada saya, “kenapa sih kamu sering pakai baju warna hitam? Apakah itu warna identitas lesbian?” Selanjutnya dia menambahkan bahwa saudara sepupunya yang lesbian juga sering pakai warna hitam/gelap. Dan cewek-cewek lesbian yang dia kenal juga sering banget pakai warna hitam.
Saya bengong lima detik sebelum akhirnya ngakak mendengar pertanyaan itu. Saya bergegas membayangkan isi lemari dan mendapati kenapa baju saya kebanyakan warnanya merah, kuning, biru, ya? Ada sih hitam, cuma kayaknya tidak membuat warna tersebut sebagai warna identitas. Bahkan jumlah baju hitam saya sama dengan jumlah baju pink yang saya miliki.
Pertanyaan tentang pakaian ini bukanlah yang pertama kalinya ditujukan untuk saya. Seorang sahabat partner juga pernah berkomentar seperti itu. Saya jadi berpikir. Kenapa ya? Lalu saya dan sahabat gay saya yang bekerja di bidang fashion itu berdiskusi. Dia bilang, warna hitam itu membuat pemakainya tampak more powerful, confident, and manly. Saya jawab, "Heh? Masa sih?" Mungkin dia benar. Tapi sejujurnya, saya suka memakai warna hitam (terutama kalau saya ada janji meeting), karena memang warna itu membuat saya merasa aman dan percaya diri. Kenapa? Karena saya orang yang ceroboh dan jorok.
Saya selalu kagum pada orang yang bisa pakai baju warna putih. Saya angkat topi buat mereka. Buat saya, memakai baju warna putih, apalagi di musim hujan sama beraninya dengan mereka yang berjalan melewati ladang penuh ranjau di Irak. Karena kalau saya memakai putih, belum jam makan siang saja, kemeja/baju saya bakal kena berbagai noda. Entah itu noda kopi, teh, atau bekas remah makanan yang bisa dengan mudahnya nempel di baju.
Jikalau sahabat gay saya bertanya (lagi) kenapa lesbian menggemari warna hitam, mungkin jawabannya karena lesbian-lesbian itu pengecut seperti saya. Mereka tidak berani berjalan sambil memamerkan ranjau tetesan kuah soto atau gado-gado sisa makan siang.
Bagian II
Gara-gara obrolan dengan sahabat gay itu, saya jadi ingat obrolan saya via chat dengan seorang sahabat gay lain. Sahabat gay saya bercerita tentang gay night yang dia hadiri. Dia bercerita bagaimana di sana dia melihat cewek butch yang sok asyik. Sebagai lelaki berperasaan halus, dia gentar melihat lesbian butch nongkrong di tempat yang seharusnya GAY night.
Dia bertanya pada saya, “Kenapa sih lesbian itu tampangnya sangar-sangar?”
Saya pura-pura sensi dong. “Maksud lo?” tanya saya balik.
“Maksud gue bukan elo. Secara elo itu kan butch feminin.”
“Maksud lo?” tanya saya lagi, yang masih sok sensi gitu deh.
“Maksud gue, kalo cowok gay kan manis, terawat, harum. Sementara kenapa sih cewek-cewek lesbi itu nggak jaga penampilan? Badannya itu lho..., nggak keurus. Belum lagi penampilan secara keseluruhan, kebapakan gitu. Eh, tapi gue bukan refer ke elo lho."
Saya pun tertawa, tidak bisa berlama-lama sensi dengan sahabat saya ini. Bagaimanapun, dia kan cuma menanyakan pertanyaan yang jujur dari lubuk hatinya. Mulailah kami berdiskusi, beranalisis tentang penampilan para lesbian. Mungkin karena lesbian kan kebanyakan hormon cowoknya gitu ya, jadi penampilannya pun jadi berlagak cowok gitu, demikian ulasan teman saya.
“Eh, elo sendiri jarang dandan,” tiba-tiba dia nyeletuk.
“Gue nggak dandan karena gue udah cantik, tauk!” demikian jawaban saya. “Tapi soal perawatan mah, gini-gini eike meni-pedi lho. Belum lagi creambath rutin, pokoknya yang namanya ke salon mah kudu deh tiap 2 minggu sekali." Biar teteup disayang istri gitu lhoooo...
Bagian III
Dalam satu acara peluncuran buku, seorang sahabat pria (yang konon katanya gay) menarik saya ke pojok ketika saya baru mengambil makanan kecil. Dengan wajah penuh konspirasi dia bertanya pada saya, “Seberapa penting sih penetrasi pada hubungan seksual lesbian? Apakah berpengaruh besar pada kemampuan orgasme?”
Saya jawab, “Idih, penting nggak sih elo pengin tau hal kayak gini?”
“Ini bukan pertanyaan iseng, tahu! Ini dalam rangka riset pembuatan novel yang tokoh utamanya lesbian.”
“So?” tanya saya. “Ngapain juga elo masukin adegan gituan? Nyari sensasi ya? Udah nggak zaman lagi, tahu!” Entah kenapa saya jadi sensi dengan pertanyaannya tentang urusan seks ini.
Sahabat saya ini yang satu ini memang sudah terkenal gila. Kadang-kadang kegilaannya menjurus ke arah menyebalkan. Tapi setelah dipikir-pikir, pertanyaan ini mungkin sering muncul di benak banyak orang yang bukan lesbian. Mungkin untuk hubungan seks sesama lelaki, mereka tidak akan bertanya dengan penuh semangat, karena kita bisa lebih mudah membayangkan bagaimana caranya.
Saya tahu kalau saya tidak menjawabnya, dia akan mencecar saya tanpa henti hingga akhir acara. Akhirnya sebelum beranjak pergi meninggalkan dia di pojok itu, saya jawab pertanyaannya secara tak acuh. "Ah, cewek lesbian itu mah paling hebat deh, nggak perlu penetrasi, dicolek aja bisa orgasme kok." Dan sahabat saya kontan ternganga sementara tangannya mengambang di udara memegang kue yang belum sempat masuk mulutnya. Hahaha, mati kutu dia. :)
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Suatu malam partner berfilosofi, “Siapa yang kaupilih jadi pasanganmu bisa menyeretmu ke jurang kehancuran atau mengangkatmu ke surga tertinggi.”
Pernyataan tersebut mengingatkan pada seorang sahabat lesbian yang sudah saya kenal lebih dari sepuluh tahun lalu. Ketika pertama kali berkenalan, sebut saja namanya Ellie, tinggal bersama partnernya di sebuah rumah petak berkamar satu di dalam gang kecil yang cuma muat dilewati sepeda motor. Waktu itu dia sedang cuti kuliah, padahal tinggal 2 semester lagi selesai dan berusaha mencari bisnis kecil-kecilan sebelum uang tabungannya telanjur ludes untuk biaya hidup. Saat itu masanya krismon menjelang akhir tahun 90-an, dan partnernya yang pengangguran mengaku sedang kesulitan mencari pekerjaan.
Deraan kesulitan ekonomi sering membuat mereka bertengkar, ditambah lagi partnernya ternyata gemar berjudi membuat hubungan mereka makin buruk. Yang satu menyalahkan yang lain. Hingga suatu hari Ellie tidak tahan dan menelepon ibunya yang tinggal di kota lain sambil menangis bercucuran air mata, tak tahan lagi. Betapa kagetnya saya ketika tahu siapa ayah Ellie, rumah petak tempat tinggalnya mungkin cuma seukuran kamar tidurnya yang megah di rumah ayahnya yang seluas lapangan bola. Ayahnya adalah seseorang yang punya nama besar di negara ini. Dan ketika mendapati putri kesayangannya lesbian, tidak ada jalan lain bagi sang ayah yang punya karakter sama-sama keras kepala seperti putrinya selain “melepaskan” sang putri untuk memilih jalan hidupnya sendiri.
Kabur dari rumah dan rela hidup susah demi cinta asal bisa bersama dengan orang yang kita cintai mungkin romantis ketika kita baca dalam novel atau tonton dalam film. Tapi kenyataan begitu keras menimpa Ellie, sampai-sampai dia jatuh bergedebuk keras hingga memar sekujur tubuh. Untungnya ibu Ellie adalah mediator andal, ia diam-diam membantu putrinya dengan mengirim uang tanpa sepengetahuan ayahnya agar Ellie paling tidak bisa terus kuliah, sambil terus mendinginkan hati ayahnya dan mengingatkan lelaki tua itu bahwa Ellie adalah anak perempuan satu-satunya dalam keluarga.
Ibunya adalah perempuan luar biasa. Ketika akhirnya saya berkesempatan bertemu dengan ibunya, dia bilang pada saya agar membantu menjaga Ellie. “Lex, tolong bantu jaga dia ya, Tante cuma berharap Ellie bisa ketemu pasangan yang baik, terserah deh laki atau perempuan. Tante nggak tahan liat Ellie hidup menderita kayak gini.”
Untungnya hati sang ayah pun perlahan-lahan ikut luluh, itu pun karena Ellie sudah putus dari pacar perempuannya karena si bajingan pengangguran itu kedapatan punya cewek lain. Agh, jangan bayangkan adegan ala sinetron di mana setelah bertengkar hebat sang ayah memeluk putri tercintanya kemudian berkata, “It’s okay, Nak. Papa nerima kamu apa adanya.” Tidak. Ayah dan anak perempuannya ini sudah melewati titik “point of no return” dan Ellie sudah tidak bisa lagi jadi gadis kecil kesayangan ayah saat memutuskan "keluar" dari rumah.
Berhentikah Ellie jadi lesbian ketika cintanya dikoyak dan dikhianati perempuan? Tidak. Dia menemukan perempuan lain yang mengisi hidupnya. Kali ini, ayah dan ibunya sudah “menutup mata”, terserah deh putrinya mau sama siapa, selama orang itu bisa menyayangi Ellie dengan baik. Kali ini Ellie menemukan perempuan karier yang sukses, yang dijamin takkan membuatnya tinggal di gang sempit. Ellie tinggal bersama sang kekasih barunya, mengikuti sang kekasih layaknya istri yang baik ketika sang kekasih ditugaskan ke luar negeri, tinggal berdua di rumah baru yang mereka beli berdua ketika kembali ke Jakarta. Ibu dan ayah Ellie pun tidak lagi menguarkan aroma kebencian saat berkumpul bersama putri kesayangan dan “menantu” mereka.
Life goes on, and sometimes shit happens. Suatu hari, selewat lima tahun hubungan mereka pupus karena konon sang kekasih berselingkuh dengan perempuan lain. Lalu mulailah episode baru patah hati yang menyakitkan ditambah perebutan harta gono-gini yang melelahkan dan seru ibarat nonton episode Insert secara langsung. Di antara kekesalan dan kekecewaannya ibu Ellie berkata, “jika Ellie bukan lesbian, sekarang dia pasti sudah punya anak dan suami yang sayang sama dia, bukannya seperti sekarang setiap beberapa tahun sekali harus sakit hati.” Penyesalan terbesar ibu Ellie ternyata bukan punya putri lesbian, tapi karena Ellie selalu menemukan pasangan yang menyeretnya ke jurang.
Saya percaya semua orang layak mendapat cinta, apa pun bentuknya. Demikian juga Ellie. Namun semestinya dia tidak perlu mencium 1000 kodok dulu agar bisa menemukan pangerannya (eh, mungkin dalam hal ini putri). Selama ini Ellie hanya menemukan kodok-kodok yang dikirannya jelmaan putri, namun nyatanya mereka cuma kodok yang hobi melompat hingga terjun bebas ke jurang dan menyeret Ellie ikut serta.
Menyesalkah Ellie terlahir sebagai lesbian? Jelas tidak.
Menyesalkah Ellie coming out pada orangtuanya? Maybe yes, maybe no.
Penyesalan terbesar Ellie adalah ia tidak mampu menunjukkan diri kepada orangtuanya bahwa dia bisa jadi lesbian yang punya hubungan solid dan pasangan yang bisa mengangkatnya ke surga tertinggi agar orangtuanya tidak selamanya menyesali dan bertanya, “Kenapa, Ellie? Kenapa?”
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Seorang selebriti pernah ditanya dalam suatu wawancara radio oleh penelepon. “Mbak, apakah mbak lesbian?”
Dug! Saya hampir jatuh dari kursi mendengar pertanyaan itu. Untungnya si mas penyiar radio tersebut dengan cerdas mengalihkan pertanyaan itu dengan menjawab secara bercanda, “Duh, Mas, kok nanya kayak gitu sih? Yang jelas lesbian itu saya. Karena saya pecinta wanita.”
Saya mengenal sang selebriti secara pribadi dan dia merupakan sosok yang dihormati, baik hati, dan ramah. Jujur, ketika pertama kali bertemu dengannya saya juga mengajukan pertanyaan yang sama, namun bedanya saya hanya mengajukan pertanyaan itu dalam hati. Setelah mengenal pribadi beliau lebih jauh daripada sosok yang ditampilkannya sebagai selebriti, pemikiran apakah dia lesbian atau tidak sudah tidak penting lagi.
Pernah juga sewaktu di Bali, bersama seorang sahabat perempuan, dan seorang selebriti lelaki kami mengunjungi kelab yang sering jadi tempat hangout gay di Bali. Saat sedang santai, kami didatangi seorang lelaki yang menyapa sahabat selebriti saya. “Mas X ya? Wah, nggak nyangka ketemu Mas di sini.” Lalu lelaki itu mengaku sebagai wartawan dan mengeluarkan kartu nama sebuah media dan ingin mewawancarai si Mas X itu jika ada waktu di Bali. Kami bertiga nyaris menahan napas bersamaan mengetahui lelaki itu wartawan... Namun untungnya si mas wartawan itu menghargai privasi sahabat selebriti saya itu dengan tidak mengajukan pertanyaan bodoh, “Mas gay ya karena mas hang out di sini?” Dengan bertemunya kami di kelab itu sudah ada pernyataan “I know you, you know me.” lah.
Majalah Out edisi Mei 2007, menampilkan cover Jodie Foster dan Anderson Cooper--jurnalis TV yang bekerja di CNN, dan memasukkan mereka dalam daftar "50 The Most Powerful Gay Men and Women in America." Yang jadi masalah adalah Jodie Foster dan Anderson Cooper tidak pernah mengklaim diri sebagai gay/lesbian, meskipun mereka juga tidak menyangkalnya. Edisi Out ini menimbulkan pro-kontra tentang seberapa jauh media boleh mempublikasikan orientasi seksual seseorang.
Yeah, memang kita biasa ketemu dengan sesama teman dan bergosip tentang seleb mana yang gay/lesbian. Namun pertanyaan pentingnya adalah seberapa jauh gosip itu bisa disebarluaskan? Apalagi di dunia maya, ketika orang bisa saja memasang foto atau menyebarkan informasi atau bergosip tentang siapa yang gay/lesbian, seperti yang baru-baru ini terjadi pada Bertrand Antolin dan Indra Brugman ketika foto dan gosip tentang mereka beredar di internet.
Tidak mudah bagi selebriti/tokoh publik yang juga gay/lesbian untuk mengungkapkan orientasi seksualnya. Apalagi di Indonesia. Selain teror yang mungkin menimpa mereka, kemerosotan karier kemungkinan besar menanti di masa depan. Tidak mudah memang. Paling-paling kita tahu sama tahu sajalah, jika dari penampilan fisik sudah keliatan jelas tanpa perlu dipertanyakan lagi.
Jangan salahkan selebriti jika mereka tidak mau coming out. Maklum, publik di sini amat garang untuk urusan begini. Jangankan ketauan sebagai gay/lesbian, sering berperan sebagai tokoh antagonis aja bisa digampar orang di jalan. Berpose di majalah Playboy aja bisa jadi berurusan sama polisi. Yah, jelas tidak ada yang mau jadi martir. Biarlah omongan selebriti/tokoh publik mana yang gay/lesbian hanya jadi omongan private. Kadang-kadang ada panggilan yang lebih tinggi dalam hidup ini selain mendiskusikan siapa pacaran sama siapa, hanya demi kepentingan kolom gosip.
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Jangan Pernah Merasa Sendirian, Percayalah Suatu Hari Kau Akan Menemukan Cinta yang Kau Cari
Dalam kehidupan normal saja, masa remaja adalah masa yang sulit untuk dilalui. Tapi jika sejak remaja kau sudah merasa bahwa kau gay/lesbian/transeksual, masa itu akan berpuluh-puluh kali lipat lebih sulit. Kesendirian dan ketakutan yang dialami remaja homoseksual sering menyebabkan timbulnya depresi yang berlebihan. Kadang-kadang bunuh diri dilakukan untuk mencegah agar orang-orang tidak tahu bahwa dia homoseksual. Selain itu desakan pergaulan atau peer pressure, tekanan orangtua, atau akibat coming out yang terlalu dini di usia muda bisa menyebabkan remaja homoseksual mengambil tindakan nekat.
Dunia remaja tidaklah seindah novel-novel teenlit atau semanis gulali. Banyak dari kita yang sudah melewati masa remaja pasti mengakuinya. Memasuki masa puber dan remaja, biasanya gay/lesbian/transeksual menyadari bahwa diri mereka berbeda dari teman-temannya karena mereka tertarik pada sesama jenis.
Perbedaan bukanlah sesuatu yang disukai oleh remaja, maka bisa kaulihat bagaimana remaja sering bergerombol ke sana kemari demi untuk jadi bagian dari suatu kelompok (dan moga-moga kau bisa masuk kelompok populer). Saat kau berbeda, kau jadi makhluk freak, nerd, atau si homo. Saat kau berbeda, kau akan jadi sasaran bullying mereka yang mayoritas. Belum lagi jika kau berasal dari keluarga yang kurang harmonis, di mana keluarga tidak bisa jadi pilar tempatmu bersandar. Meskipun keluarga harmonis juga tidak menjamin 100% anak tidak melakukan bunuh diri.
Bayangkan betapa takutnya dirimu saat mengetahuinya. Kau tentu tidak mau dipanggil si homo, banci, lesbi, bencong, lines, atau apalah sebutan lainnya selama di sekolah, kan? Atau bahkan kau bisa dipukuli di sekolah setiap hari karena alasan bahwa dirimu “beda”. Rasa takut dan bingung itu membuat banyak remaja seakan-akan merasa berada dalam lubang hitam tergelap dalam hidupnya. Saya sendiri pernah mengalaminya. Satu kali. Berpikir untuk mengakhiri hidup agar orang tidak perlu tahu bahwa saya lesbian. Dan kini tiap hari saya bersyukur niat itu hanya sebatas niatan dan saya tidak jadi melakukannya. Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan seperti itu.
Bunuh diri sering dianggap sebagai cara mudah untuk menyelesaikan masalah. Apalagi karena remaja berpikir masih dengan amygdala, sehingga segala keputusan biasanya dilakukan atas dasar emosi bukannya nalar. Alexander Stevens, Asst. Professor di Oregon Health and Science University, menjelaskan bahwa otak remaja adalah “pekerjaan yang belum selesai.” Riset terbaru menyatakan jaringan saraf di otak bagian depan yang diperlukan untuk membuat keputusan, menyelesaikan masalah, dan berpikir secara logis dan nalar baru akan selesai terbentuk pada usia 20 tahunan.
Akibatnya remaja sering mengambil keputusan berdasarkan emosi sesaat tanpa dipikirkan akibatnya kemudian. Tapi ini juga yang menyebabkan cinta yang dialami oleh remaja terasa begitu indah karena emosi mereka membanjir mengalir drastis dalam otak mereka.
Oleh karena itu coming out, tidaklah disarankan untuk kaum remaja terutama yang masih berusia di bawah 19 tahun. Cobalah untuk beradaptasi sekarang, kau bisa coming out nanti kalau kau sudah sukses dan berprestasi sehingga debu pun menyingkir saat kau hendak berjalan. Coming out butuh kemandirian diri yang amat sangat besar dan pertimbangan rasional yang dipikirkan secara saksama, bukan dilakukan secara impulsif.
Banyak yang tidak merasa aman untuk “come out” dengan orientasi seksual mereka. Dan sayangnya, mereka benar. Banyak remaja GLBT yang jadi sasaran siksaan fisik dan verbal. Dan bullying terus-menerus ini bisa mendorong bunuh diri. Sumber: http://www.suicide.org/gay-and-lesbian-suicide.html
Proses penerimaan diri seseorang menyadari bahwa mereka gay/lesbian/transeksual adalah proses yang panjang berliku dan menyakitkan. Semakin muda seseorang menyadari orientasi seksualnya, semakin banyak kebingungan dan kesulitan yang mereka hadapi yang bisa mendorong risiko terjadinya pikiran atau tindakan bunuh diri. Biasanya mereka yang bunuh diri adalah mereka yang secara fisik tampak “berbeda”. Transeksual yang tidak tahan harus menjadi orang yang bukan dirinya juga banyak yang berpikir untuk mengakhiri hidup mereka. Banyak lesbian/gay yang setelah melewati usia 20 tahun akhirnya memutuskan untuk kompromi, terutama terhadap keluarga dan juga melakukan adaptasi sosial.
Menurut statistik di Amerika Serikat tahun 2001 dari situs http://www.suicide.org/, remaja usia 15-24 meninggal akibat bunuh diri setiap 2 jam 12 menit. Dan kurang-lebih 30%-nya adalah remaja gay/lesbian/transeksual. Menurut data statistik dari http://www.lambda.org/youth_suicide.htm, 35% gay dan 38% lesbian pernah serius berpikir untuk bunuh diri.
Di Indonesia sendiri menurut majalah Tempo dalam terbitan Maret 2007, tidak ada data pasti tentang statistik bunuh diri di Indonesia. Dan sayangnya, di Indonesia kepedulian terhadap tingkat bunuh diri ini sangat rendah. Hampir tidak ada referensi pencegahan bunuh diri atau hotline untuk remaja yang bisa ditemukan untuk menangani hal ini. Padahal support group amat diperlukan dalam hal ini.
Masalah bunuh diri ini bukanlah karena “perbedaan” orientasi seksual, tapi lebih kepada cara memandang hidup. Tidak ada seorang remaja pun, homoseksual atau hetero, yang seharusnya berpikir untuk melakukan bunuh diri. Percayalah suatu hari kau akan menemukan cinta yang kau cari. Ingatlah bahwa kau tidak sendirian. Dirimu terlalu berharga. Bunuh diri bukanlah jawaban. Carilah bantuan.
Klik beberapa situs di bawah ini untuk memulai langkah awal mencari bantuan jika ada teman atau kau sendiri yang punya niatan mengakhiri hidup.
http://www.suicide.org/index.html
http://www.lambda.org/youth_suicide.htm
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Aku ingat saat pertama kali ibumu memberitahuku bahwa dia hamil. Begitu banyak perasaan yang mengaliriku saat itu. Yeah, mommy-mu yang satu itu selain keras kepala, memang penuh kejutan. Aku ingat malam-malam bergelung di ranjang bersama mommy-mu dengan perutnya yang buncit. Dengan mood swing-nya yang kadang-kadang membuatku berjalan di atas titian bambu :). Oya, Nak, sewaktu mengandungmu, aku sering bilang pada mommy-mu bahwa dia adalah perempuan hamil terseksi. Sungguh, mommy-mu memang luar biasa seksi kala itu.
Aku ingat ketika menemani mommy-mu ke dokter kandungan setiap bulan. Berdua duduk di kursi tunggu mulai dari perut mommy-mu yang masih rata hingga perutnya sebesar pompa air. Aku ingat ketika melihatmu di layar USG mulai dari bintik kecil yang membuatku bertanya pada sang dokter, “Di mana, Dok? Kok nggak keliatan?” Dan si dokter berusaha keras menunjukkannya padaku.
Aku ingat ketika hari kau dilahirkan setahun lalu. Awal-awal bulan yang menghebohkan. Malam-malam zombie, ketika aku dan mommy-mu bergiliran tidur hanya 2 jam untuk meninabobokanmu. Dulu hobiku adalah menidurkanmu sampai-sampai kau hanya bisa ditidurkan dalam buaianku, hingga mommy-mu pernah stres berat dan membuatku tunggang-langgang pulang menjelang tengah malam karena kau muntah dan tidak mau tidur kecuali dalam pelukanku.
Aku ingat ketika kau sakit yang bikin cemas semua orang, apalagi kau menangis tanpa henti dan hanya bisa ditenangkan oleh mommy-mu. Hiks, rasanya ingin ikutan menangis melihatmu kala itu. Namun di saat seperti itu ada momen fun ketika mommy-mu mengajakmu berendam di bathtub untuk menurunkan panasmu. Duh, mommy-mu yang satu itu memang penuh ide.
Nak, kita punya ritual pribadi antara kita berdua yang bahkan membuat mommy-mu terheran-heran. Kita berdua bisa cekikikan saat membuat susu botolmu setiap malam. Atau ketika kita tertawa riang sewaktu bermain balon. Atau acara korek kuping yang membuatmu keenakan hingga liurmu menetes. Semua itu adalah momen berharga yang kubingkai rapi dalam ruang hatiku.
Aku ingat langkah pertamamu yang membuat aku dan mommy-mu menahan napas ketika kau jatuh tersungkur. Mommy-mu meneleponku ketika untuk pertama kalinya kau bisa berjalan. Fiuhhh... betapa serunya menyaksikan kau berjalan mulai dari langkah malu-malu hingga berusaha berlari.
Semalam mommy-mu bilang, “Say, tahun depan kita nggak punya baby lagi.” Yup, mommy-mu betul. Tahun depan kau sudah tidak bisa dibilang bayi lagi. Selamat ulang tahun yang pertama, Nak. Dan seperti yang sering kubisikkan di telingamu tiap malam. “I love you, baby. Very Much.”
@Alex, RahasiaBulan, 2007
Pay It Forward
Kecapi koleksi sederhana tentang retrospeksi hidup, kronik harian, atau apresiasi hiburan direkat dalam mozaik sketsa lesbian.
Selamat datang. Aku si bulan itu. Dan ini rahasiaku.
Alex Lagi Ngapain Ya?
Jejaring SepociKopi
-
Club Camilan13 years ago
-
Topik: Sisterhood Unlimited!14 years ago
-
Surga Kepulauan Raja Ampat14 years ago
-
Kian Damai16 years ago
-
-
Jejaring Sahabat
Komen Terbaru
Kategori
- lesbian (79)
- film (63)
- Personal Life (51)
- Opini (40)
- Intermezzo (38)
- buku (29)
- TV (14)
- persona (12)
- gay (11)
- remaja (10)
- Asia (9)
- love (7)
- biseksual (5)
- coming out (4)
- poem (4)
- subteks (4)
- L Word (3)
- transeksual (3)
- South of Nowhere (2)
- Lakhsmi (1)
- cinta (1)
- lagu (1)